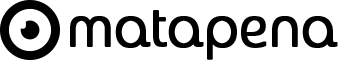Kedunguan Atavis
Suka dan memang sering kesepian
Tidak ada salahnya mempercayai, meniru, dan melakukan hal-hal yang dilakukan dan diajarkan oleh para pendahulu (baca: taklid). Asalkan taklid—saya lebih senang menyebutnya dengan atavisme—tersebut dilakukan dengan filterisasi dan kontemplasi yang matang. Atau, orang Jawa mengatakannya dengan dipun penggalih kanthi wening lan dipun pikir kanthi jangkep (terj: direnungkan dengan khidmat dan dipikirkan dengan matang).
Bukan berniat mengglorifikasi ajaran Jawa, tetapi sebagai bentuk pendeknya wawasan saya—karena itu yang saya tahu sebab saya juga etnis Jawa. Soal atavisme, orang Jawa bisa kita jadikan contoh yang baik dalam menerapkannya. Wening-nya penggalih dan jangkep-nya pikir, melahirkan produk-produk atavistik yang sudah dimodifikasi dengan baik. Islam Jawa misalnya, bagaimana kita bisa melihat betapa ritual berkumpul dan pesta untuk merayakan sekaligus meratapi kematian, dimodifikasi dengan begitu romantis menjadi tahlilan. Betapa wayang kulit disunting dengan begitu indahnya menjadi sarana dakwah yang menghibur. Contoh lain sangatlah banyak. Tak usah disebutkan satu-per-satu. Sebab, bukan itu tujuan pembahasan kita sekarang.
Yang menjadi masalah adalah jika produk-produk atavistik dihasilkan melalui kedunguan (baca: taklid buta). Warisan-warisan “tetua” dipahami dan diresapi secara vulgar.
Mari menilik apa yang terjadi saat kemunculan Humanisme di abad Pencerahan. “Kecelakaan”, atau kesalahan—bebas menyebutnya dengan apa, yang dirasai dengan begitu telanjang. Peresapan secara vulgar tersebut, dalam Humanisme, akhirnya menjadikan trauma tersendiri. Hingga muncullah Humanisme Ateis, yang bahkan membuat manusia men-Tuhan-kan diri, atau pikirannya sendiri. Membuat manusia bukan hanya “terlepas” dari sosok transendental, tetapi “menjadi” sosok transendental itu sendiri. Lebih buruk, manusia-manusia yang dianggap sebagai Manusia—meminjam istilah yang dibuat oleh Budi Hardiman, memakai m kapital untuk menyebut manusia versi Humanisme Eropa—adalah manusia-manusia yang sesuai dengan klasifikasi manusia yang dibuatnya. Hingga kemudian muncullah Antroposentrisme/Euro-sentrisme. Memandang orang-orang yang bukan orang Eropa dan “peradabannya” bukan sebagai Manusia. Lalu timbul lah kolonialisme dan imperialisme yang mereka sebut sebagai “pemberadaban” dan “pe-Manusiaan” kepada manusia-manusia non-Eropa.
Dalam kasus tersebut, yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan (dan penyalahan) dalam memaknai agama dan Tuhan. Di mana gereja dan penguasa menggunakan agama, Tuhan, dan “dunia-sana” sebagai alat untuk menghegemoni, menginfantilisasi, bahkan mengebiri imanensi manusia. Yang seharusnya disalahkan adalah konsep pemikirannya, bukan agama atau Tuhan-nya. Seharusnya berhala-berhala pikiran yang dihancurkan, bukan bangunan-bangunan agama.
Saya harus akui saya terlalu naif, karena membawa peristiwa tersebut untuk menganalogikan kasus yang terjadi di sekitar saya. Kasus yang saya maksud adalah “netralitas semu” yang lahir dari kedunguan atavis di salah satu organ intra di kampus saya. Saya tidak mau membahasnya dengan persepektif politik atau ideologis. Saya ingin membahasnya dari perspektif kemanusiaan. Ya, karena cuma itu yang saya tahu. Dan untuk ukuran mahasiswa semester 3 seperti saya, membahas politik dan ideologi adalah hal yang cukup menggelikan—bagi para pendengar atau pembacanya. “Anak baru kemarin kok sudah membahas politik dan ideologi, haha. Habis minum apa kamu?” seperti itu mungkin tanggapannya.
Iya, saya memang tidak mau muluk-muluk dan kesusu membawanya kepada “kecacatan demokrasi”, sebagaimana disebutkan oleh Chantal Moufe, yang disebabkan oleh nihilnya konfrontasi agonistik antar-elemen. Saya juga tidak mau membahasnya melalui “sinisme” ataupun “fantasi ideologis”-nya Zizek. Tidak, saya hanya membahasnya melalui sudut pandang kemanusiaan. Untuk itulah saya menganalogikannya dengan peristiwa historis Humanisme.
Seperti sejarah Humanisme, kasus ini juga sebenarnya disebabkan oleh kecelakaan sejarah yang diresapi secara telanjang dan vulgar. Saya tidak perlu menjelaskannya, tulisan Rizal Kurniawan tahun lalu, https://matapena.id/sebuah-curhat-tentang-ketakutan-laten/, mungkin sudah cukup menggambarkan soal “kecelakaan sejarah” yang terjadi, juga di dalamnya terdapat kasus yang mirip dengan yang saya bahas. Masalahnya tetap sama sebenarnya, meminjam istilah Rizal Kurniawan dalam artikel tersebut, “ketakutan laten” yang kemudian menimbulkan sentimen buta.
“Kecelakaan sejarah” tersebut, pada akhirnya juga menimbulkan antroposentrisme—mari menyebutnya dengan intra-sentrisme, yang memandang manusia-manusia yang ikut organ ekstra, yang bukan golongan mereka, yang berbeda dengan “peradaban” mereka, akhirnya—meminjam istilah Marx—dialienasikan. Tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya yang bisa mendapatkan hak seperti yang lainnya. Usaha-usaha “pemberadaban” juga pernah dilakukan, seperti dituliskan oleh Rizal Kurniawan dalam https://matapena.id/sebuah-curhat-tentang-ketakutan-laten/: “Apakah kamu ikut ekstra?, kamu harus memilih, organisasi ekstramu atau organisasi yang sekarang kau daftari ini” .
Namun, kali ini kasusnya agak sedikit berbeda. “Ketakutan laten” timbul lagi dengan slentingan, “Jangan sampai anak ekstra berkumpul dalam satu divisi. Bahaya!”. Ya, seperti itu lah. Manusia-manusia yang ikut organ ekstra seakan dianggap sebagai “anak setan” yang harus dicurigai dan diwaspadai. Dan bahkan sebenarnya saya sendiri juga tidak mengerti yang dimaksud dengan “bahaya” itu seperti apa.
Slentingan itu muncul saat ada rencana pembentukan divisi, dan di dalamnya ada dua orang organ ekstra, dan orang yang dicurigai dekat dan akan gabung dengan organ ekstra—padahal sebenarnya tidak, persangkaan seperti itu mungkin timbul dari sentimen yang sudah mendarah daging dan diwariskan secara turun-temurun. Akhirnya usaha pemisahan dilakukan untuk menghindari “bahaya” tersebut. Lalu, tiga orang—termasuk saya—memilih untuk tidak jadi bergabung (yeay, bebas! Haha, akhirnya tidak jadi “anak setan” lagi…), lebih memilih berproses di organ lain yang menerima kami apa adanya, tidak ada sentimen maupun “ketakutan laten”. Miris memang, formasi yang dari awal terbangun karena landasan objektif: minat, kapasitas, dan kualitas per-individu tiba-tiba dirobohkan dengan sentimen atavistik—ketakutan laten yang turun-temurun. Tentu yang diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan tidak seperti itu, selalu ada alasan lain untuk menutupinya. Dan alasan-alasan penutupnya juga tak begitu masuk akal.
Ada lagi “wahyu” yang berbunyi: “Jangan sampai anak ekstra menduduki posisi strategis”. Aah, apa lagi ini? saya tak berani komentar. Ada lagi, ocehan-ocehan kecil, tapi cukup bisa membuat “gerah”. Ya, meminjam kalimat salah seorang teman, hal-hal seperti inilah yang disebut “pemangkasan dan penghilangan potensi karena sentimen belaka”.
Atavisme yang dilandasi dengan kedunguan dan sentimen belaka ini seharusnya tidak terjadi—lagi. Saya paham niat baiknya adalah ingin melakukan sebuah reformisme yang radikal atau bahkan revolusi: membuat organisasi menjadi bersih dan netral, atau tidak ingin “kecelakaan sejarah” itu terjadi lagi. Namun, yang menjadi persoalan adalah niat tersebut malah membuat manusia-manusia, yang dicurigai dapat menyebabkan “ketakutan laten” tersebut benar-benar terjadi, menjadi teralienasi. Sehingga, yang terjadi bukan lagi reformisme radikal atau revolusi, melainkan reformisme mandul. Datar-datar saja. Tenaga yang seharusnya digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat “laju” organisasi semakin kencang, malah terbuang sia-sia untuk menuruti “ketakutan laten” yang secara atavistik diwariskan dengan kedunguan.
Ya, modifikasi atavisme mesti segera dilakukan ke depan. Demi kebaikan organisasi sendiri. Jalan-jalan untuk menutup kemungkinan “ketakutan laten” benar-benar terjadi mesti diubah. Bukan lagi dengan alienasi manusia-manusia yang bahkan tidak paham dengan apa yang dimaksudkan dan terjadi. Tetapi dengan penguatan “diri” dan perbaikan sistem yang diharapkan dapat membuat “ketakutan laten” yang diwariskan secara atavistik itu tidak terjadi lagi. Dan juga, penggalih yang wening dan pikiran yang jangkep sangatlah diperlukan dalam bertindak, jadi bukan hanya kemanutan dan overdosis intervensi, apalagi sentimen belaka.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip Marcus Aurelius dalam Meditation-nya: “Cara terbaik untuk balas dendam adalah dengan tidak bertingkah laku seperti orang yang menyakitimu.”.
Terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa makan!
Penulis: Muhammad Rizqi Hasan
Editor: Azza Masruroh Nur
Ilustrasi: https://www.guioteca.com/psicologia-y-tendencias/%C2%BFcomo-desarrollar-la-fuerza-de-voluntad/
Suka dan memang sering kesepian