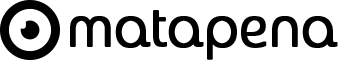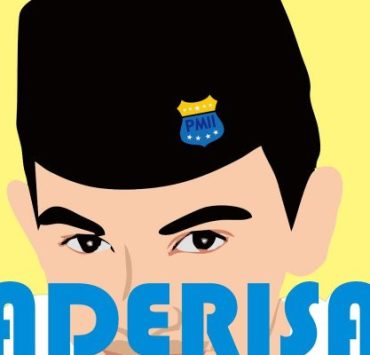Membenci Dawet

Joko tingkir ngombe dawet
Jo dipikir marai mumet
Ngopek jamur nggone mbah wage
Pantang mundur terus nyambut gawe
Apa yang salah dengan kalimat Joko Tingkir “ngombe” dawet? Jika kalian baru saja membaca empat larik di atas dengan bernada—atau setidaknya punya naluri ritmis dengan lagu itu. Hal itu membuktikan bahwa pencipta lagu tersebut berhasil menemukan apa yang disebut-sebut penyair sebagai bahasa. Membuat siapapun yang mendengarkannya memiliki ingatan yang panjang.
Apakah tidak termasuk suatu hal yang hiperbolis (berlebihan) jika lagu tersebut dianggap menghina Joko Tingkir karena beliau adalah sosok ulama besar di Jawa? Jika saya boleh membayangkan, bukankah ulama-ulama kita terdahulu seperti Walisongo justru lebih dekat dengan nasi tumpeng daripada nasi kebuli? Bukahkah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita lebih gemar melahap singkong atau umbi-umbian daripada kurma dan air zamzam? Lagian apa buruknya sih dengan es dawet? Bukankah ngombe dawet adalah rutinitas yang tidak menyimpang secara syariat? Pekerjaan “ngombe” itu halal dan minumannya juga minuman halal? Beda lagi jika liriknya Joko Tingkir ngombe iceland. Itu jelas kurang ajar dan layak ditentang—meskipun jika dilihat dari konteks sastrawi tidak dianggap sebagai satu hal yang debatable. Joko Tingkir tidak akan diabetes meminum es dawet karena gula yang dipakai adalah gula aren, kemungkinan terburuknya bagi adalah kolesterol sebab minuman bersantan.
Jika “ngombe dawet” dianggap sebagai frasa yang mengandung problem, bukankah justru mereka yang punya asumsi itu telah secara tak sadar sedang merawat logika yang serba terbalik? Coba deh saya kasih analogi, siapa yang tidak mengenal Gus Baha atau Habib Ja’far, satu seorang kiai kampung, satu seorang Habib, dzurriyah Rasul. Kira-kira, mereka lebih senang dan nyaman mana jika diperlakukan sebagaimana orang pada umumnya atau mereka disanjung-sanjung dan dielu-elukan setiap detik? Saya rasa, orang waras akan menjawab pilihan pertama. Terlalu berlebihan membela apa yang sebenarnya tidak perlu dibela adalah penyakit lama, namun mempermasalahkan dawet sebagai bentuk penghinaan adalah kedunguan, setidaknya pada dasawarsa terakhir ini.
Sialnya, yang melemparkan wacana “Joko Tingkir ngombe dawet” sebagai penghinaan adalah dua pendakwah besar di Jawa Timur. Mengapa kita selalu punya obsesi tinggi memperseterukan suatu hal yang seharusnya tidak perlu dianggap serius? Menganggap kalimat “Joko tingkir ngombe dawet” sebagai bentuk penistaan adalah sama halnya dengan menganggap bahwa ulama adalah titisan malaikat dengan pekerjaan yang tidak manusiawi. Padahal, kalimat itu justru membantu kita untuk memikirkan kembali bahwa ulama atau orang yang faham ilmu agama jugalah manusia, ulama juga berhak jandoman di pos kampling, mendekatkan diri dengan masyarakat. Tidak malah asyik menggelar sajadah, dan sujud berlama-lama namun lupa akan kondisi sosial masyarakat di sekelilingnya. Bukankah tingginya ilmu justru membantu kita untuk menjadi “manusia” yang seutuhnya?
Padahal jika mau mendalami teks lagu tersebut, bukankah lirik-kiriknya sangat motivasional? Mengajak kita agar tidak terlalu memikirkan urusan (duniawi)—sebab hidup hanya permainan dan senda gurau belaka? Mengajak kita agar tetap berusaha dan bekerja meskipun rejeki sudah ada yang mengatur. Lihat, bukankah itu sevisi dengan apa yang dicita-citakan Joko Tingkir ketika beliau masih hidup dulu? Memberikan pegangan hidup pada masyarakat dan mengajaknya untuk mengimani apa yang sudah tertulis dan ditakdirkan .
Ronald Dwi Febriansyah, sebagai pengkarya sampai harus mengucapkan kata minta maaf sebanyak 14 kali dalam video klarifikasi di akun Youtubenya @TamaHalu008 yang berdurasi dua menit lima belas detik tersebut. Rasa salah yang menurut saya tidak perlu, meskipun matanya mengisyaratkan sebuah kesedihan yang mendalam sebab ketidaktahuan. Gitu masih ada yang berkomentar “Seharusnya sebelum bikin lagu harus mempertimbangkan unsur sosio-historisnya!” Asyu tenan, saran itu cocok gawe mahasiswa-mahasiswa yang kuliah jurusan etnomusikologi ISI Yogya kae, gak matching dan relevan buat orang semacam mas Ronald. Berani menciptakan lagu dan dikenal masyarakat luas sudah menjadi kebanggan tersendiri bagi dirinya.
Perubahan lagu dari kalimat “Joko Tingkir ngombe dawet” menjadi “Mbah Amer ijik ngaret suket” adalah satu bentuk kekalahan sistemik wong cilik pada apa yang disebut sebagai superioty. Lirik boleh diubah, tapi apakah memori kolektif masyarakat dengan Joko Tingkir ngombe dawet dapat terlupakan? Saya kira tidak.