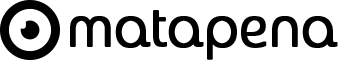Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) lahir dari rahim idealisme yang berani dalam tetang kekang untuk kebebasan dunia pers yang diinisiasi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) lantaran pemberlakuan NKK/BKK menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978, Daoed Joesoef. Latar belakang SK Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan tersebut guna meredam aktivitas mahasiswa dalam dunia politik dan mengimbau agar mahasiswa fokus belajar di kampus.
Akibatnya, IPMI mulai lepai dengan pembatasan ruang geraknya juga terutama dengan adanya Badan Kerja Sama Pers Mahasiswa Indonesia bentukan Orde Baru. Orde Baru melancarkan keputusan ini menyusul banyaknya mahasiswa yang beroposisi dengan pemerintah, tidak terkecuali melalui penerbitan pers.
Kedudukan pers yang sentral inilah yang menggugah semangat mahasiswa IPMI untuk mengadakan sebuah kongres yang kemudian melahirkan PPMI. Kongres pertama yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya tanggal 15 Oktober 1992 membidani lahirnya Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia. Tiga tahun berselang dalam kongres kedua tanggal 14 Desember 1995, di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jember melahirkan Deklarasi Tegal Boto dan perubahan terhadap nama “Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia” menjadi “Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia”.
Potongan sejarah tersebut betapa merekam keterlibatan penting LPM Tegal Boto dalam perjuangan meneguhkan eksistensi pers kampus di Indonesia. Beberapa dekade telah berlalu, realitas berubah silih berganti. Namun, sejarah gemilang itu alih-alih senantiasa menjadi pecut idealisme untuk terus menjadi semakin maju dan profesional, LPM, sekarang berubah jadi Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa (UKPKM) Tegal Boto malah mati suri—bersama BEM Univ. yang sekarang masih belum menunjukkan gelagat hidup kembali—hampir dalam kurun waktu tiga tahunan sejak pandemi menyerang dan kampus memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Seharusnya belum lama ini saya memperingati peringatan seribu hari kematiannya. Akan tetapi, baru-baru ini UKMKM Tegal Boto membuka pendaftaran anggota baru.
Skeptisisme dari beberapa kalangan kating saya terhadap lembaga pers ini sudah lama menghantui kepala. Seorang mahasiswa akhir yang juga wartawan bercerita pengalamannya sekitar empat tahun mengamati gelagat beberapa organisasi pers mahasiswa di tingkat fakultas dan tingkat universitas, nyatanya sama saja: hidup segan mati tak mau. “Mereka hanya menghasilkan berita straight news secara momentuman. Hanya ketika selesai mengadakan acara-acara baru nulis.”
Lebih lanjut, ia berujar: siapa yang bisa menjamin oprec ini bisa menjadi awal kekonsistenan lembaga tersebut? Open recruitment hanya sebuah formalitas administratif saja. Apakah selesai oprec Tegal Boto akan kembali aktif lagi?
Pertanyaan itu seolah kembali meyakinkan saya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan Pemimpin Redaksi masa khidmat 2022. Dari percakapan tersebut saya mengetahui bahwa pers Tegal Boto sudah mati suri. Menurut pengakuan sang pem-red, terdapat permasalahan internal yang akut. “Mereka masuk pers, tapi pas sudah masuk, mereka nggak mau belajar. Aku sedari awal sudah berusaha menggonggong sana-sini tapi tidak ada yang punya tekad kuat,” ujarnya. Ia merasa UKM-nya amat tidak solid. Setiap kali sang pem-red mengajak pengurus-pengurusnya untuk berkumpul, berdiskusi, hampir semua pengurus selalu ada alasan untuk mengelak. “Dan itu terjadi semenjak aku masuk, bahkan sebelumnya. Pers kampus sudah kehilangan taring sejak beberapa tahun ke belakang, dan sulit sekali untuk mengembalikannya,” tandasnya.
Manajemen redaksi yang baik, iklim diskusi ruang redaksi yang berkualitas, produk jurnalisme yang kredibel, dan tetek-bengek lainnya, harus membutuhkan waktu berapa lama bisa terbentuk, ditambah semangat awak redaksi yang musiman. Hal ini merupakan masalah yang serius kalau masih mau menganggap pers sebagai pilar keempat (the fourth estate) demokrasi. Selain itu, kemampuan literasi mahasiswa akan menurun kualitasnya, terutama dalam hal tulis-menulis. Jurnalisme kampus melatih mahasiswa untuk peka dan reflektif terhadap permasalahan sosial di sekitarnya, memperjuangkan hak-hak/independen, senantiasa menyoal integritas kekuasaan, memunyai kerangka berpikir yang sistematis dan tidak cacat logika sehingga bisa menghasilkan tulisan yang apik.
Mungkin dengan terburu-buru saya bisa simpulkan kalau jurnalisme kampus adalah sumber dari terbentuknya kritisisme mahasiswa. Saya sengaja tidak memperhitungkan ruang kelas sebagai sebuah laboratorium penghasil kritisisme. Sebab saya mengalami sendiri realitas ruang kelas di FIB Unej—di sini saya tidak hendak menggeneralisasi. Bagaimana ruang kelas kami hanya cukup mengajarkan teori-teori lama (meski begitu, kami sudah gagap menerimanya) dan jangankan memproduksi pikiran-pikiran baru, tulisan akademik yang kami hasilkan saja masih memalukan. Hal tersebut mungkin lantaran kami membeli tas yang tidak didesain untuk membawa buku sehingga dengan sendirinya tidak pandai menulis.
Kalau sumbernya sudah mati, siapa lagi yang bakal menjalankan fungsi watchdog—menggonggongi aparat universitas dan pemerintah daerah, mengawal setiap kebijakan, dan menagih visi-misi—di tengah kampus yang tidak ada BEM-nya, sehingga tidak ada lagi wadah penyambung lidah dan penyampai aspirasi. BEM dan pers kampus dimaksudkan supaya penguasa tidak berusaha membahagiakan mahasiswanya tapi dengan ukuran penguasa itu sendiri.
Tantangan “melawan” humas kampus
Apakah kampus hanya akan memiliki semangat zaman kehumasan yang mengandaikan citra baik di atas segalanya tanpa memperhitungkan esensi sebenarnya? Seperti gelagat pemerintahan rezim ini yang cenderung tidak memiliki integritas dengan pasukan buzzerp, sewenang-wenang, korup, memanipulasi hukum, menyuap, dan tentu mengintervensi kebebasan pers. Demokrasi, kita tahu, mewajibkan diri memiliki oposisi kalau tidak mau kekuasaan akan sewenang-wenang.
Lingkungan kampus juga demikian. Contoh, isu-isu santer yang saya dengar dari mahasiswa kampus tetangga yang memiliki jembatan dengan anggaran 2 M, mengatasi demo mahasiswa terkait UKT yang mahal dengan sewa preman-preman, dan kemarin, lokasi wisuda yang tumben di satu hotel mewah, bukan di aula kampus yang sedang tidak terpakai. Usut punya usut, menurut mahasiswa sana, pagi sampai siang digunakan untuk acara wisuda, sore sampai malam digunakan buat acara pernikahan anak rektor.
Bukan tidak mungkin kampus saya juga akan menjiplak kebijakan lucu sekaligus represif macam itu. Dengan kekuatan public relation yang kuat, kampus saya cenderung mementingkan citranya daripada esensi belaka. Untuk saya sebutkan, kampus saya sering mengadakan lomba twibbon dengan penghargaan yang tidak kalah dengan hadiah lomba paper. Tujuannya tentu buat menaikkan citra. Kebiasaan mem-branding nama secara instan tersebut memicu kebijakan semacam: Unej mendaku sebagai green campus tapi tanpa konsep dan program keberlanjutan yang jelas. Green campus tidak akan cukup hanya bermodalkan rerimbun pohon sedang tempat sampah tiap hari sesak dijejali plastik dan stirofoam. Ada juga dosen yang mewajibkan mahasiswanya mengikuti webinar rutinnya, memberi mahasiswanya tugas me-review tulisannya di jurnal fakultas dengan akses mandiri untuk meningkatkan daftar kunjungan, dsb.
Sependek pengamatan, tak banyak saya temui suara-suara oposisi dari mahasiswa untuk kebijakan-kebijakan aparatur kampus. Apakah kampus saya ini sudah mencapai idealnya, sehingga tidak perlu berbenah dan bertransformasi berarti lagi? Atau karena jurnalismenya yang tidak jalan sehingga kritisisme mahasiswa ‘tak terlihat’? Atau malah saya yang tidak menemukan suara-suara oposisi karena terhijab oleh muntahan informasi dari humas kampus?
Dari sini kita tahu tantangan bagi LPM Pers Tegal Boto adalah, bagaimana kiat Pers Tegal Boto mengambil eksistensinya dengan mengasuh berita di web, buletin, dan majalah. Sedangkan kampus dengan kekuatan sumber daya humasnya konsisten membuat konten semacam berita di laman media sosialnya dan di website resminya. Saya belum yakin dengan sumber daya manusia baru semacam saya bisa menerbitkan buletin bahkan majalah dalam waktu dekat dan konsisten, sehingga saya pikir mungkin kru-kru persnya hanya akan rutin bikin berita di website. Apa mungkin eksistensi pers Tegal Boto hanya ketika buat berita tentang keburukan kampus karena berita-berita bagusnya sudah ditangani humas? Ujung-ujungnya dibredel lagi kalo terus-terusan menganulir citra baik bentukan humas.
Saya sedang menunggu kebijakan dan strategi apa yang akan diterapkan untuk menyiasati hal ini. Barang tentu saya masih memelihara harapan supaya UKM ini bisa kembali maju seperti masa lalu. Agaknya mahasiswa lebih suka bikin meme shitpost daripada bikin tulisan yang bisa dimuat di surat kabar. Terakhir, saya ingin menyitasi isi buku ‘A9ama’ Saya Adalah Jurnalisme karya Andreas Harsono: Kovach berpendapat, “Makin bermutu jurnalisme di dalam masyarakat, maka makin bermutu pula informasi yang didapat masyarakat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat.” Saya percaya, apabila jurnalisme di suatu masyarakat bermutu, maka kehidupan masyarakat itu juga akan makin bermutu.
penulis: Haikal F.
ilustrasi: Fatmawati
seonggok homo unius libri