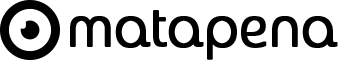Sepotong Roti yang Harus Dibagi

“Saat ini, ibu Anda sudah berhasil melewati masa kritisnya. Namun, kami tidak bisa menjamin bahwa kondisinya akan tetap stabil seperti ini.”
“Berikan yang terbaik untuk perawatan ibu saya, Dok.”
“Kami terus berusaha memberikan perawatan yang terbaik untuk membuatnya bertahan.”
Percakapan sore itu terus menggelayuti pikirannya. Ingin rasanya umpatan terhadap kehidupan yang sial ini meluncur dari bibir, akan tetapi ia cukup sabar untuk menahan. Kini dipandangnya tubuh wanita yang kurus dan layu terbaring di atas brankar, sebuah selimut melingkupinya hingga dada. Sudah tujuh tahun tubuh itu tidur, meninggalkan putrinya yang mati-matian mencari cara untuk tetap bertahan hidup.
Kedua bola matanya memanas, air mulai keluar untuk kembali mendinginkan penglihatan. Tak mau menahan lebih lama lagi, wanita berusia seperempat abad itu memutuskan untuk keluar dari ruangan. Menyusuri lorong rumah sakit yang tetap terasa suram meski hari ini cukup banyak orang berlalu-lalang. Rasa yang melilit tiba-tiba menyerang perut, seperti ada sensasi terbakar yang bersarang di antara perut dan dada. Lambungnya bermasalah, alih-alih mencari obat atau pertolongan selagi masih di rumah sakit, ia lebih memilih untuk duduk di kursi panjang ruang tunggu.
Air mata yang sejak tadi ditahannya kini sudah membanjiri pipi. Ternyata rasa sesak di dada dan sakit di perutnya sehebat itu untuk menahannya tidak menangis di tempat umum. Beruntung, tempat ini tidak begitu banyak orang. Yang duduk dan pergi bahkan tidak menyadari keberadaannya, tenggelam dengan rasa sesaknya masing-masing, mungkin. Cepat-cepat ia menghapus air matanya ketika seorang gadis kecil menghampiri dengan senyum manis merekah.
“Kakak menangis?” tanya anak itu dengan raut wajah penasarannya.
Senyum perempuan itu mengembang lalu menggeleng pada anak kecil di hadapannya.
Tangan mungil gadis itu membawa sepotong roti yang menguarkan aroma kopi, dengan hati-hati dibelahnya roti tersebut menjadi dua bagian. Satu bagian di tangan kanan disodorkan pada wanita di depannya yang berusaha merapikan rambut sebahunya agar tidak menghalangi pandangan. Sedangkan sepotong di tangan lainnya untuk dirinya sendiri. Saat memasukkan potongan itu ke dalam mulut, raut wajah anak itu seakan menginginkan wanita itu melakukan hal yang sama.
Perlahan digigitnya potongan roti tersebut. Rasa kopi yang langsung memenuhi mulut dan hawa dari oven yang belum sepenuhnya hilang membuat hatinya menghangat. Krim keju yang meleleh menambah rasa asin manis yang meredakan asam lambung. Seakan memastikan pemberiannya sudah dimakan, gadis kecil itu berlari meninggalkan wanita itu sendirian, menghampiri seorang dokter yang tadi ditemui oleh Nira. Pria berjas putih itu memberikan tos pada gadis kecil, lalu memandangi wanita yang duduk menikmati setengah potong roti.
Gadis kecil itu berhasil mengembalikan segaris senyum tipis di bibir Nira, menghangatkan hatinya, dan melemparkan ingatan ke beberapa tahun silam, tahun-tahun dipenuhi rasa sakit karena sepotong roti. Masih ingat betul ketika ibunya meneriakinya untuk selalu berbagi pada sang adik, atas apa saja yang ia dapatkan. Jika tidak, maka piring-piring akan beterbangan, mendarat di lantai dan tak jarang kepingannya berserak ke penjuru sudut rumah yang kecil. Sebuah pembelaan pada anak laki-lakinya agar mendapatkan semua yang diinginkan. Tak peduli jika itu membuat anak perempuannya kelaparan, atau berdarah akibat goresan beling yang tajam.
“Nira! Adikmu itu dikasih sedikit. Kamu ini jangan makan banyak-banyak!” teriaknya dari dapur diiringi suara perabotan yang dicuci dengan kasar.
“Tapi adik sudah makan satu, Bu, roti ini memang sudah bagianku.”
Suara bising dari dapur mendadak hening, derap langkah terdengar semakin mendekat dan sosok ibunya muncul dari balik kelambu coklat lusuh. Kedua tangannya yang basah dilap ke daster hijau yang sudah terperciki air cucian piring. Air muka wanita paruh baya itu terlihat kesal karena putrinya membantah ucapannya.
Tanpa basa-basi, direbutnya sepotong roti dari tangan Nira kemudian dibelah menjadi dua dengan tangan yang belum sepenuhnya kering. Menelisik mana bagian yang lebih besar, itulah yang diserahkan pada anak laki-laki. “Kamu ini sudah besar, harus mengalah sama Bagas,” ucapnya dengan nada bersungut, tetapi ketika menyerahkan potongan besar itu pada Bagas, wajahnya tersenyum dengan nada bicara yang dilembutkan. “Bagas ini calon orang sukses, harapan kita. Harus banyak makan biar sehat.”
“Kenapa, sih, Ibu selalu mengutamakan Bagas daripada aku? Kenapa sejak Bapak meninggal, Ibu nggak pernah adil? Semua buat Bagas, apa-apa selalu Bagas. Aku ini juga anakmu!”
“Kamu sudah terlalu banyak dimanja sama Bapakmu, Bagas itu laki-laki dan kamu Cuma perempuan. Tugasmu ngabdi di rumah dan Bagas harus bisa menjadi tentara atau polisi nantinya. Ibu lebih bahagia kalau anak-anak ibu semua laki-laki,” ucapnya tanpa memandang Nira sedikit pun. hanya ada Bagas yang bersinar di matanya. Tak lama kemudian ia melangkah kembali ke dapur.
Nira mengikuti langkah kaki ibunya dengan rasa sakit di hati. Ia hanyalah seorang gadis yang seharusnya mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi harus dikorbankan karena ibunya lebih ikhlas membiayai Bagas. Padahal, adiknya itu masih kelas lima Sekolah Dasar. Tak apa jika ia harus merelakan mimpinya, tetapi apakah sepadan dengan rasa sakit yang ia dapatkan saat ini? Nira terus memupuk rasa benci terhadap sang adik yang bisa mendapatkan segalanya.
“Ibu selalu pilih kasih. Bahkan aku tidak pernah mengeluh kalau harus kerja, tapi ibu tidak pernah menghargai apa yang aku capai dan hasilkan dari kerja kerasku sendiri.”
“Aku tidak pernah menunggu capaianmu, Nir. Itu sudah kewajibanmu membantu ibu membiayai sekolah adikmu karena Bapakmu meninggal. Itu pun dia meninggal gara-gara selalu berusaha menuruti keinginanmu, toh?”
Apakah salah jika Nira menginginkan sepotong roti seperti yang dimakan Bagas dengan gembira bersama teman-temannya sedangkan dia hanya melihat dari balik pintu? Tiga tahun lalu, Bapak Nira mendapatinya memandang ke luar bukan dengan rasa iri, tetapi hanya ingin merasakan apa yang dimakan oleh saudara kandungnya. Bapak Nira memang tidak menyuruh Bagas berbagi rotinya, ia lebih memilih untuk membeli agar anak-anak merasa senang. Namun, sialnya hingga sore menjelang, Bapak tak kunjung pulang. Salah seorang warga melapor bahwa Bapak mengalami kecelakaan, tepatnya ditabrak oleh sebuah mobil. Di tangannya, sebuah kantong kresek berisi sepotong roti telah dingin dan berdebu.
Dadanya terasa sesak, Nira seperti dihantam batu besar dan tidak diberi kesempatan untuk bernapas, tenggorokannya tercekat. “Ibu nyalahin aku?” tiga kata yang lolos dari bibirnya membuat bendungan air mata meluruh tak tertahankan.
Perempuan itu pikir, ibunya akan memberikan penjelasan, atau sekalian membenarkan pertanyaannya. Namun, amarah yang sudah menguasai membuat wanita paruh baya itu berteriak geram. Ia berbalik badan, pisau berada di genggaman tangan kanan, dan wajahnya memerah tetapi juga menahan tangis. “Hidup miskin itu melelahkan, Nira! Lelah! Dan satu-satunya yang ibu jadikan sebagai harapan untuk sukses hanyalah Bagas.”
Nira terisak, serasa hilang pikiran hingga sebuah pertanyaan kembali terlontar, “Kenapa bukan aku, Bu?”
“Karena kamu perempuan. Kita cuma perempuan, Nira!” teriaknya sambil melempar pisau tersebut yang sialnya terarah kepada Nira.
Sepersekian detik jika ia tidak bisa menghindari pisau itu, entah mata atau bagian lainnya mungkin sudah menjadi sarang bagi benda tajam tersebut. Dinding yang terkena sasaran pun terkelupas permukaannya hingga segaris bata merah dapat terlihat. Dua langkah mundur, Nira menempel di dinding dan merosot ke lantai. Batinnya bergejolak, Ibu melempar pisau padaku.
Bagi Nira di tahun berikut-berikutnya, yang harus dilakukan hanyalah menghasilkan uang, memberikan sebagian besar pada Ibu untuk membiayai pendidikan Bagas, dan sebagian kecil lainnya untuk membeli kebutuhan pokok. Sang adik yang dielu-elukan akan menjadi tentara atau polisi sehingga bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan, nyatanya ia hanya menghabiskan waktunya untuk tidur di siang hari dan berkeliaran saat malam. Shift malam, alasannya pada Ibu, tetapi Nira tahu bahwa adiknya adalah pemabuk yang bermain-main dengan kartu serta bertaruh tumpukan uang.
“Kamu ini selalu berprasangka buruk sama adikmu, Nir. Dia Cuma kerja sampingan dan main sama teman-temannya untuk melepas stress persiapan seleksi militer.”
“Bagas nggak akan bisa masuk akademi militer, Bu. Dia itu pemabuk, Ibu saja yang tidak pernah lihat kondisi dia saat pulang lewat tengah malam. Calon siswa militer pun juga akan terlihat rajin berolahraga untuk menjaga tubuhnya, tapi Bagas tidak.” Nira membeberkan apa yang dilihatnya selama ini, yang selalu diabaikan oleh sang Ibu. “Menghabiskan uangku saja,” gerutunya hampir berbisik.
“Nira, kamu nggak berhak iri sama adikmu. Adikmu itu laki-laki yang memang sepatutnya punya posisi yang terpandang dan harus sukses.”
“Ibu terus saja membela dia. Kalaupun dia sukses, itu juga berangkat dari kerja kerasku menghasilkan uang untuk biayanya. Nyatanya sekarang dia menjadi pemabuk dan penjudi. Kalau ibu menilai aku iri, Ibu benar, tapi mulai sekarang tidak lagi peduli dengan Bagas. Toh, tidak ada yang peduli juga dengan hidup dan matiku, aku tidak perlu peduli dengan siapa pun.”
“Berdosa kamu, Nir, sudah menyumpahi adikmu!”
“Aku nggak pernah menyumpahi, Bu, aku cuma nggak akan peduli lagi sama dia.”
Adu mulut antara ibu dan anak itu masih berlangsung, memperkeruh suasana dengan suara yang makin terdengar oleh tetangga. Mungkin mereka sudah bergunjing tentang kehidupan mereka yang sangat mengenaskan. Sejak kepergian bapak, Nira tahu bahwa ia tak akan lagi mendapat keadilan dari orang tua satu-satunya yang masih hidup. Ia paham bahwa menyerah bukan pilihan yang bagus, tetapi bertahan juga membuatnya tersiksa.
Teriakan yang saling tumpang tindih tersebut seketika hening saat pintu rumah mereka digedor semakin keras. Panggilan dari luar pintu menginterupsi mereka untuk segera merespons. “Keadaan gawat, kalian harus menolong mas Bagas.”
Mendengar nama anak kesayangannya disebut, sang ibu langsung bergegas membukakan pintu. Seorang remaja yang umurnya tak lebih dari lima belas tahun berdiri ketakutan. Menjelaskan tentang apa yang telah ia lihat sebelumnya. Di sebuah lorong sepi yang hampir tidak pernah dilewati orang-orang, terlebih di malam hari, ia mengendap-endap. Rasa curiganya semakin kuat saat ada suara samar-samar yang meneriaki nama tetangganya. Lebih mendekat lagi, remaja itu melihat Bagas terkapar di tanah dengan mulut penuh busa.
Nira tak bisa memungkiri bahwa ada rasa sesak sekaligus takut yang kini menyerangnya. Padahal, sudah jelas hatinya berteriak tak peduli lagi dengan Bagas. Dialihkan pandangannya pada ibunya yang kini sudah berwajah pucat. Jiwanya seperti terenggut paksa tanpa aba-aba. Wanita paruh baya itu berusaha kuat melangkahkan kakinya yang gemetar untuk keluar mencari keberadaan buah hatinya. Namun, tepat sebelum melewati pintu, tubuh itu terasa lemas. Belum sempat tangannya mencari pegangan pada kusen pintu, ia sudah meluruh ke lantai.
Jantung Nira berdentum hebat hingga detik ini saat mengingat peristiwa tersebut. Dipandangnya setengah potong roti di tangannya yang sudah dingin, kemudian sedikit demi sedikit dihabiskan. Ia mulai terisak lagi tanpa suara. Rambut sebahunya jatuh saat kepala Nira menunduk. Malam itu adalah malam di mana Nira akan memutuskan takdirnya sendiri, kehidupannya akan berubah mulai saat itu. Ibunya jatuh koma saat mengetahui Bagas sekarat karena overdosis narkotika. Bagian paling mengenaskannya adalah, adiknya itu meninggalkan sejumlah utang dari transaksi judi, dan selama empat tahun lamanya Nira baru bisa melunasi utang tersebut.
Entah sudah berapa lama waktu yang dihabiskan di ruang tunggu ini, hari semakin larut. Tanggung jika harus pulang ke rumah sewanya di pinggiran kota. Mungkin akan lebih baik jika bermalam di sini. Untuk pertama kalinya Nira memutuskan hal tersebut. Semalaman menunggui sang ibu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Ada sebersit kerinduan yang amat dalam, tetapi masih saja tak mampu menggeser rasa sakitnya yang sudah mengakar.
Perlahan ia memasuki lagi ruangan ibunya dirawat. Tak banyak peralatan bantu, hanya pendeteksi jantung karena tubuhnya sudah cukup lemah. Nira memandang sekilas, bagaimana pun, meski ibunya sadar juga tak mau tahu bahwa satu-satunya orang yang peduli padanya hanyalah Nira seorang. Helaan napas kasar lolos dari mulutnya sembari mendaratkan pantat di kursi samping brankar.
“Akhirnya selalu aku kan, Bu? Yang selalu ada dan membiayai hidupmu hingga akhir. Bukan, ini bukan masalah uang. Tapi, tentang bagaimana ibu selalu memperlakukan aku. Sebesar itukah perbedaanku dengan Bagas? Apakah anak perempuan tidak akan memberikan barang setitik saja keberuntungan untuk orang tuanya? Bahkan anak berandalan itu hanya bisa menghamburkan uang, berperilaku tidak baik, dan berakhir mengenaskan. Apa yang ibu puaskan dari anak yang seperti itu?”
Nira meletakkan tas yang sedari tadi menggantung di bahu lalu mengecek ponselnya. Beberapa pesan dan panggilan tak terjawab bertengger di notifikasi, tetapi tak dihiraukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nira menyentuh tangan ibunya, digenggam dengan lembut.
“Bu, katakan, jika ibu terlalu merindukan anak laki-lakimu, maka temui saja. Barangkali tubuh ini terlalu menyiksamu. Kita berdua sama-sama sakit, Bu. Aku tetap rela jika ibu memang lebih menyayangi Bagas, dari pada aku.”
Dikiranya tangan Nira sendiri yang semakin erat menggenggam, ternyata bukan. Ia menyadari bahwa tangan ibunya juga bergerak, membalas genggaman tangan putrinya. Hati Nira sempat membuncah bahagia, tetapi seketika diliputi kebingungan karena alat pendeteksi jantung semakin acak dalam memberi sinyal. Ia memahami kondisi ini dan segera memencet bel darurat. Kurang dari satu menit para perawat dan seorang dokter memasuki ruangan.
“Harap Anda menunggu di luar dulu,” ucap seorang perawat perempuan sambil menyentuh bahu Nira pelan. Tanpa ada penolakan, kakinya segera melangkah meninggalkan ruangan tersebut, melewati pintu dan melepaskan segara firasat.
Menit demi menit berlalu lama di atas kursi tunggu di lorong selasar. Lamunannya mendadak buyar ketika mendengar suara pintu terbuka, menampilkan seorang dokter muda yang sering ditemuinya karena bertanggung jawab atas perawatan sang ibu. Pria itu tidak menunjukkan ekspresi apa pun, membuat Nira menebak-nebak hasilnya. Dengan jubah putih bersihnya, pria itu mendekat, berbicara dengan lembut.
“Jantungnya sudah sangat lemah, sangat sulit untuk menyelamatkannya kali ini.”
Hati Nira teriris, ia tidak bisa berpikir dengan jernih. “Bukannya tadi siang dokter sudah mengatakan bahwa ibuku baik-baik saja?”
Dokter itu memandang lawan bicaranya, memberikan perhatian penuh yang jelas berbeda dengan pandangan terhadap keluarga pasien lainnya. “Kita tidak bisa menebak keadaan yang akan datang. Sekarang keputusan ada di tanganmu.”
Pelan dan samar, Nira mengangguk, kemudian menunduk dalam-dalam. Ia sudah memberikan persetujuan untuk menghentikan seluruh tindakan penyelamatan. Ia tidak tahu keputusannya benar atau salah. Mungkin, ini juga yang diinginkan ibunya, bertemu Bagas sesegera mungkin.
Keesokan harinya, prosesi pemakaman ibu Nira telah usai. Tak banyak orang datang, hanya pengurus makam dan beberapa kenalan. Kini, wanita itu masih menatap lekat-lekat pusara sang Ibu seorang diri. Dengan pakaian hitam, ia berlutut di samping. Menaburkan kelopak-kelopak mawar yang masih segar. Derap langkah samar terdengar dan semakin keras saat Nira mencari sumber suara tersebut. Seorang pria, tubuh yang biasanya dibalut dengan jas putih kebanggaan, kini dibalut dengan kemeja biru muda dan celana krem.
Pandangan Nira kembali menunduk, ia membuka suara ketika pria itu berhenti tepat di sampingnya. “Aku sudah menjadi orang yang bebas sekarang. Tapi, kenapa aku merasa sebagian dari diriku ikut menghilang?”
Pria itu ikut berlutut, tak memedulikan celana kremnya yang menyentuh tanah basah. Tangannya melingkar di bahu Nira, memberikan usapan lembut yang diharap bisa menenangkan. Tanpa diduga, wanita di sampingnya ini justru menyurukkan wajah ke dadanya disertai tangisan yang pecah. Ia bisa merasakan tetesan air mata yang membasahi pakaian serta menetes ke celana. Ini adalah kali pertama bagi dirinya dipeluk oleh seorang wanita, rasa gugup dan sedikit panik tiba-tiba melingkupinya.
Perlahan pria itu menepuk punggung Nira, lalu berkata, “Semua akan baik-baik saja. Aku tahu kamu wanita yang kuat, selalu menjalani kehidupan tanpa putus asa. Aku ada di sini, mulai saat ini kamu tidak akan sendirian. Ada aku, kamu bisa membagi semua keluh kesahmu padaku.”
Bagai disambar petir, Nira yang tak pernah mendengar kalimat setulus itu, kini mendongakkan wajahnya. Menyadari bahwa ia sudah memeluk dokter muda ini, Nira cepat-cepat mengendalikan diri dan mengusap air matanya. Namun, kalimat yang baru saja didengar tak bisa membendung rasa haru. Apa benar-benar ada orang sebaik dan setulus ini? Ia sangsi, akan tetapi hatinya sungguh berharap akan seseorang yang seperti itu.
Menjelang siang, Nira memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia masih menetap di rumah sewanya yang lama, akan membayar tunggakan empat bulannya dan memperpanjang lagi. Meski rumah itu tak begitu layak huni—banyak kerusakan dan kebocoran, Nira tetap mempertahankan karena uang sewanya yang cukup murah. Kini keduanya berjalan keluar dari kompleks pemakaman, masuk ke mobil mewah warna putih yang terparkir di luar pagar.
“Apa tidak merepotkan pekerjaanmu kalau harus mengantarku?” tanya Nira saat ia dibukakan pintu penumpang.
Pria berbaju biru muda tersebut menggeleng sambil tersenyum. “Hari ini tidak ada jadwal, aku bisa mengantarmu pulang,” ucapnya yang kemudian pandangannya beralih ke sekitar, entah melihat apa, “tunggu di sini, aku akan kembali.” Bergegas ia menjauh dari mobil setelah menutup pintu.
Nira memandangi bagian dalam mobil yang bersih dan rapi, tak ada barang-barang tidak berguna. Kendaraan ini terkesan kosong, ia hanya merasakan pendingin ruangan dan pewangi yang menyapa penciuman dengan lembut. Tak lama, pemilik mobil datang dengan kantong plastik yang sudah buram akibat uap dari benda panas di dalamnya. Setelah masuk dan duduk di kursi kemudi, disodorkan kantong tersebut pada Nira. Ia menerima, membuka kantong tersebut untuk mengetahui isinya. Dua potong roti.
Senyum terkembang di bibirnya, menyiratkan rasa terima kasih. Dua potong roti ini kembali mengingatkannya tentang sepotong roti yang harus dibagi kepada adiknya dengan tidak adil. Bagi sebagian orang dewasa, mungkin roti bukanlah apa-apa. Namun, bagi Nira, sepotong roti adalah sesuatu yang menjadikannya dewasa dengan kuat. Sesuatu yang menjadikannya tidak mudah menyerah terhadap permasalahan. Dan sepotong roti, membawanya pada perpisahan serta pertemuan yang tak pernah ia duga.
pengarang: Cindy Amelia
cerpen ini dinobatkan sebagai juara 1 pada lomba cerpen tingkat nasional oleh UKM Forum Studi Islam Mahasiswa Pertanian, Fakultas Pertanian Univ. Jember.