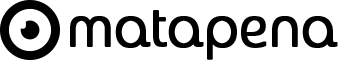Amperreh, Uti’, dan Perihal Ikan-ikan di Desaku
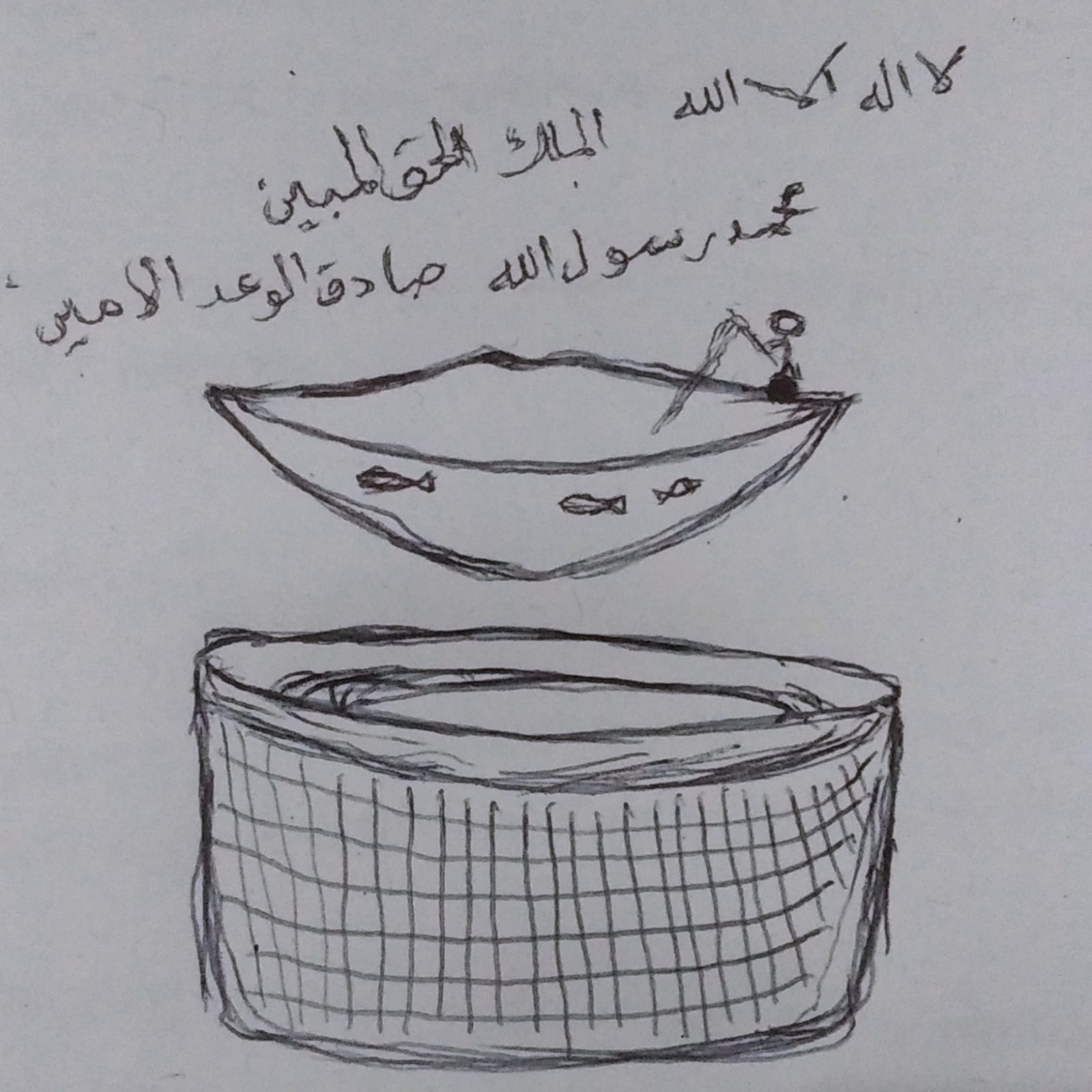
Kumandang subuh sudah membengap telingaku lebih dulu ketimbang Ibu yang masih tertidur berbalut mukena yang tak benar-benar putih lagi. Kuperhatikan di pinggir matanya sudah mulai membentuk kerut lembap hasil perjalanannya melewati berbagai kemelut sembap. Walau sayu ia masih tak benar-benar memperlihatkan gelagat layu bila mataku tertuju pada tahi lalat di atas bibir sebelum tubir tempatku duduk sambil menunggu ikan memakan kail pancing yang kulepas ke sungai bibirnya. Aku ingin meraba pipi kanannya yang senantiasa rindang.
La ilaaha illallaah, al-malikul haqqul mubin… Muhammadur rosulullaah, shodiqul wa’dil amiin… zikir Pak Indra di masjid terdengar mendayu-dayu berpadu bersama suara kodok yang suntuk mengaji di barat rumah.
Mata Ibu kemudian merekah perlahan, mungkin karena berangsur sadar merasa ada kehangatan dari embusan nafasku yang menimpa punggung tangannya. Aku diam menatap mata yang baru terbit. Denyut kehidupan keluargaku perlahan mulai berdetak. “Sudah subuh, Nak..” Tangannya yang melingkar di dadaku sejak tadi berpindah ke pipi kananku. Ibu curang, harusnya aku yang lebih dulu bisa mengelus pipinya.
Ibu kemudian beranjak dari kasur menuju tempat salat di belakang lemari lalu subuh di sana. Mataku tak sengaja terkatup kembali sampai Bapak membuka pintu seusai salat berjamaahnya di masjid. Suara derit engsel pintu yang telah lama kukenal itu yang membangunkanku. Mataku masih berat tentunya. Ibu kemudian datang ke kasur kembali untuk berbisik, “sudah subuh ‘kan, Nak?” aku mengangguk mewakili mulutku yang masih terlalu sepat untuk berbicara meski, “iya..”
Tangannya halus menyibak selimut perlahan dari tubuhku. Meski keberatan—mengingat tadi malam hujan dan gedek di sebelah ranjang tempatku tidur masih lembap—aku tak berkutik, membiarkannya menyibak sepenuhnya. “Pasti kamu mengingatnya, Nak. Ada banyak wader sebesar telapak tanganmu bermain ke hilir di sumber. Apakah kamu mau menangkapnya lagi?”
Ibu mendudukkanku. Ia masih pergi ke selatan ranjang dan dapur untuk mengumpulkan baju-baju dan beberapa peralatan dapur yang kotor ke dalam satu ember. Sekali aku takluk oleh kantuk dan baru membuka mata kembali, buyar oleh tawarannya yang kesekian kali, “benar kamu tidak mau ikut?”
Aku melompat dari kasur menuju dapur, mengambil keranjang nasi yang biasa Bapak dapatkan kalau datang kondangan. Lalu menyusul Ibu.
Di jalan aku mengucek mata yang masih lengket. Menyeberangi jalan yang masih dilalui oleh tukang ojek membonceng ibu-ibu yang datang dari pasar dengan barang berjubel. Melewati halaman masjid lalu menuruni undakan bebatuan di antara dua pohon beringin. Sampai di bawah Ibu menyuci bagiannya bersama dua tetangga kami yang sudah sampai lebih dulu, sedangkan aku berjongkok di hilir sumber yang bermata air dari bawah pohon beringin ini. Suara kodok sahut-menyahut, semakin ingar-bingar.
Ada banyak wader berwarna gelap yang seperti kata Ibu, sedang bermain ke hilir bila hari masih lelap. Betul saja, ketika ada satu wader yang lewat untuk kembali ke hulu itulah aku segera mencegatnya dengan jaring dan meski dalam air tidak ada gaya gravitasi, gerak luwes ikan itu tetap kalah cepat dengan gerak cekatanku menjaringnya dan semena-mena melontarkannya ke atas. Dan ikan bersama air terbang sebelum menuju tanah. Tak peduli basah aku segera mengamankan wader yang tak henti melompat di antara serakan daun kuning beringin. Selesai di genggaman aku menoleh ke arah Ibu, rupanya di sana Ibu dan tetangga-tetangga lain sudah mengamati seraya tertawa mengeleng-geleng. ”Ada-ada saja kelakuanmu, Nak!” itu kata Bu Sumiyati sebelum menatap Ibuku. Aku menunjukkan genggaman tangan kanan dan gigi lantaran bangga.
Bila yang pulang adalah seekor gabus aku sedikit harus menambah konsentrasi. Sebab gabus lebih cepat dan lebih luwes daripada wader ditambah warnanya yang masih lebih gelap. Gabus pandai mengecoh, berenang zig-zag atau lurus menjurus menembus ruang antara kedua betisku. Tapi aku tak pernah menyerah. Aku akan mencegat sekali lagi.
Ini adalah seekor gabus berukuran sedang yang sudah memenuhi perjalanan malamnya. Aku menantinya yang masih berenang malu-malu dari satu batu ke batu lain menuju arahku. Aku fokus melihat matanya. Agak susah karena penerangan di sumber hanya dari satu lampu yang bergantung di sela tangkai pohon beringin. Gabus itu berenang kembali semakin mendekatiku. Dan, ia hinggap di bayangan sandalku! Aku bersiap, dadaku berdebar. Fokus ..
“Deni!! Ikanmu! Di bungkus detergen itu! Melompat, dua!!”
Aku segera tergeragap, gabus untuk kesekian kalinya lolos. Aku berlari menuju tempat di mana kutaruh ikan-ikanku di pinggir bebatuan. Kulihat, ikan-ikanku mulai berhamburan. Aku panik!
***
“Apa benar ini anak sampean, Pak? Dia tadi lama sekali mandi di dam Pelalangan, di rumah saya. Saya tanya dia barusan orang mana karena sebelumnya saya tidak merasa pernah melihat anak ini. Orang Pasarejo katanya. Jadi saya antar ke sini. Saya khawatir sama dia,” bapak itu adalah orang yang baru kutemui namun menyebalkan.
“Ya ampun. Mengapa bisa sampai ke dam Talang di Pelalangan kamu, Nak? Maaf sekali, Pak. Terima kasih banyak telah repot mengantar anak saya ke sini,” sahut Bapak.
“Tidak apa-apa, Pak. Soalnya dia adalah teman anak tetangga saya di rumah. Kalau begitu saya permisi,” kemudian bapak menyebalkan itu meminta diri meninggalkan rumahku. Kemudian Bapak memarahiku. Saat kutatap takut wajahnya, rambutku masih belum kering.
“Sudah Bapak bilang kan kalau siang-siang jangan pergi main ke mana-mana, apalagi sampai ke desa lain. Kamu ingin diculik Amperreh[1], ditempatkan di atas pohon yang tinggi lalu diberi makan kotoran kuda yang akan kamu lihat sebagai roti? Kamu mau tak bisa pulang ke sini lagi, hah?!”
Aku diam. Ibu datang mendinginkan kepala Bapak. Betapa tidak, ini bukan kali pertama aku kabur dari rumah untuk main bersama teman-teman pada waktu sepulang sekolah. Akhirnya Bapak mereda dan cepat menyuruhku untuk tidur di kasur. Tak ada dongeng Uti’ dengan tubuh hanya sebesar ulekan Ibu yang selalu aku dengar menjelang tidur dari mulut sang pendongeng ulung, Bapak.
Di kasur aku kedinginan. Badanku panas-dingin meski tak lama bisa tertidur, bisa tidur mungkin lebih karena kecapaian.
Sebelum benar-benar tidur aku masih mengingat bagaimana ketika siang tadi aku mengendap-endap keluar rumah sesudah menanggalkan serangan putih-merahku dan menggantinya dengan kaos bergambar Gundam yang sedikit aus dan celana sepak bola. Kugeletakkan di atas kasur tanpa kubereskan—setelah berhasil mengapit jaring yang hanya kutaruh di bawah lincak di emperan selepas menjaring ikan subuhnya—aku langsung berlari ke belakang masjid. Mujurnya Bapak masih belum pulang dari sawah sedang Ibu tidur di kasur, sementara ke Ibu aku hanya pamit pergi ke rumah sepupu—walaupun tak ada jawaban barang anggukan. Setelahnya, aku bisa berjalan lengang dengan teman lainnya menuju dam untuk mandi dan menangkap ikan. Meski diliputi cemas karena sudah waktu zuhur aku mempertimbangkan niat urungku dengan teman-teman yang sudah terlanjur datang menjemput ke desaku ini. Jadi aku tetap berangkat.
***
Sore waktu bangau pulang ke haribaan utara aku baru terjaga. Duduk di lincak selasar rumah alih-alih bisa segar badanku masih terasa hangat bahkan panas, tapi sore ini rasanya dingin sekali. Belah kepalaku berdenyut bergantian. Hidungku tersumbat. Aku akhirnya memanggil-manggil Ibu di dalam rumah. Dipapahnya aku kemudian ke atas kasur. Wajahnya khawatir menatap wajahku yang pucat menggigil. Bapak datang melihat keadaanku dengan seksama. Dari sorot matanya ia berucap, “sepertinya ada yang tidak beres.”
Malamnya aku ganti baju Ben 10 kesayanganku dan aku benar-benar sakit. Tubuhku demam tinggi. Seingat, aku tak pernah sakit kepala sesakit ini. Bukan hanya itu, anehnya dalam penglihatanku aku ditindih batu besar: di perut, kedua tangan, dan kedua kaki. Batunya besar sekali sehingga mencapai genteng rumah. Karenanya aku hanya bisa terlentang dengan mata agak terbelalak di atas kasur. Rasanya sakit sekali. Membingungkan. Bahkan, aku yang merasa bahwa ada gempa bumi yang tak henti-henti, Ibu dan Bapak hanya tampak diam saja melihat keanehanku. Itulah sebabnya aku meraung-raung tak jelas meminta untuk dibawa keluar rumah karena aku takut rumahku akan rubuh lalu menimpaku. Tapi setengah sadar aku tahu Ibu menjawab, “di luar hujan, Nak,” dan aku tetap tak peduli serta tak dipedulikan.
Bagian telingaku sudah basah. Aku tak henti menangis dari tadi. Memekik, sesekali kalap walaupun selalu takluk dalam cengkeraman tangan Ibu dan Bapak. Ibu komat-kamit mulutnya, demikian pula Bapak. Dan setengah sadar lagi aku protes, ”Berhenti komat-kamit, Bu, Pak!” Mendengar itu keduanya tercekat, “loh, Ibu sedang baca Ayat Kursi, Nak. Mengapa kamu suruh berhenti?” aku tak menghirau, tetap menyeracau, Ibu menoleh ke Bapak sambil mulai mengundang halimun ke pelupuk matanya.
“Ini pasti ada kaitannya dengan kejadian tadi siang, Buk.”
“Mengapa bisa, Pak. Ada apa?”
“Kata orang yang mengantarkannya pulang ke sini, Deni mandi berlama-lama di dam Talang, kemungkinan besar ia masih menangkap ikan di sana. Katanya, Deni termasuk orang baru di dam Talang desa Pelalangan. Aku yakin penunggu dam itu marah kepada Deni karena sebagai orang baru ia sudah bertindak kurang sopan di sana. Makanya ia jadi begini. Kamu juga terlalu menuruti apa yang ia mau.”
“Maaf, Pak.”
“Lihatlah, begitu kasihannya dia kesambet seperti ini. Sekarang ia masih tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Bagian dirinya masih ada yang mengintervensi. Kita bisa bijak hanya dengan menerima ini dan mendoakan Deni supaya lekas sembuh. Berhentilah menangis, ini tak akan berlangsung lama.”
“Iya, Pak,” Ibu selalu menjawab singkat.
Ibu mengelus keningku setelahnya. Bapak mengambil mushaf mengaji di sampingku. Ibu hanya komat-kamit dan berupaya meredakan tangisnya sedangkan aku masih meraung-raung menyerapah apapun. Derai air mataku masih berlangsung. Sebenarnya aku ingin cepat-cepat bisa tidur.
Dalam keadaan sadar yang tak sepenuhnya aku hanya bisa ingat dua hal: satu, bahwa di luar hujan semakin deras. Dua, bahwa yang mengelus keningku sambil meredam suara tangisnya ini adalah Ibuku, perempuan pemilik tahi lalat di atas bibir sebelum tubir.
[1] Folklor sosok legenda perempuan cantik dengan rambut menjuntai namun berkaki kuda yang sering menculik anak kecil pada siang hari terutama yang belum balig dan belum bersunat.
28-10-2020 Istana Pers Jancukers
*Haikal F., bergiat di beberapa sumber, sungai, brog, dan dam.
seonggok homo unius libri