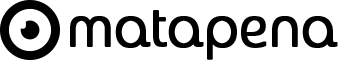Bahasa yang Arbitrer Versus Bahasa Baku

Seno Gumira Adjidarma, mengatakan kalau bahasa adalah unsur kebudayaan terpenting tetapi termasuk yang paling diabaikan. Indonesia dengan fasilitas bahasa daerah yang meruah, tidak memiliki penghargaan sungguh-sungguh terhadap bahasa-bahasa daerah sehingga kehilangan penutur dan akhirnya beberapa bahasa daerah punah. Sebuah ironi akibat lemahnya imunitas kebudayaan kita terhadap gerakan globalisasi yang menghendaki homogenisasi budaya dalam satu kebudayaan tunggal bernama modernitas, sehingga kebudayaan marginal tersisih, sebelum terlindas.
Berawal dari itu, bahasa seyogyanya harus dijaga, dirawat, dan diruwat. Bahasa Indonesia adalah identitas yang tidak boleh diganti dan dihegemoni oleh bahasa lain. Goenawan Mohamad, pendiri majalah Tempo berujar bahwa dia sangat bersyukur memiliki bahasa Indonesia. Sebab, bahasa ini dibentuk dari berbagai bahasa daerah (Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Melayu, Sansakerta, dsb) dan bahasa pendatang (Belanda, Arab, Cina, dsb) tanpa terdapat bahasa yang hegemonik daripada yang lain, sehingga bahasa Indonesia ini sangat mencerminkan demokrasi.
Akan tetapi, makin ke sini, puak milenial semakin tidak menghargai bahasanya sendiri, ditandai dengan munculnya tren nginggris atau bahasa jaksel, yaitu kebiasaan berbahasa dengan mencampuri antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini dianggap keren dan terkesan lebih berpendidikan karena bahasa Inggris yang notabene adalah bahasa Internasional. Akan tetapi, pada kenyataannya fenomena seperti di atas justru menunjukkan ketidakmengertian akan hakikat bahasanya sendiri, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang buruk juga merupakan representasi dari ketidakcintaan atas bahasa sendiri. Beberapa hal tersebut mungkin akibat sikap apatis yang disebabkan oleh kebiasaan puak milenial yang tidak suka belajar sejarah negeri mereka sendiri, terlepas dari beberapa sebab lain.
Di luar dari itu, apa pengertian dasar tentang bahasa? Secara gamblang, bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Fungsinya adalah untuk berinteraksi, bekerja sama antar satu anggota masyarakat dengan yang lainnya, dan untuk mengidentifikasikan diri. Bahasa terdiri dari kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf. Dari kata-kata tersebut membentuk kalimat, dan wacana. Kata sendiri merupakan simbol/penanda sebagai representasi dari satu konsep/petanda.
Dalam upaya membentuk kata/simbol/penanda, dikenal satu konsep bernama arbitrer. Arbitrer dalam buku “Dunia yang Berlari” karya Yasraf, diartikan sebagai; konsep semiotika yang menyatakan bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak berdasarkan hubungan alamiah, melainkan diada-adakan atau semena-mena.
Jadi, kesemena-menaan itu dibentuk juga oleh konvensi masyarakat penutur. Dari sini timbul pertanyaan, kalau masyarakat mengonversi bahasa mereka sendiri dengan semena-mena, perlukah membuat kategori baku-tidaknya bahasa? Sedangkan kita tahu, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-lah rujukan bahasa baku. Hal tersebut kelihatannya agak menyalahi fungsi arbitrer bahasa. Seolah kebakuan bahasa ditentukan oleh segelintir orang yang bernama Tim Penyusun KBBI.
Seperti contoh, penghilangan huruf H pada kata hadang, himbau, hisap, hentak, hembus yang sudah dimutakhirnya menjadi tidak baku. Di kalangan masyarakat kebanyakan mungkin masih belum mengetahui beberapa kata tersebut sudah dikategorikan menjadi kata tidak baku. Padahal dalam kesehariannya, masyarakat menggunakan beberapa kata di atas seperti sedia kala, dengan huruf H.
Inilah yang disebut oleh penyair Saut Situmorang sebagai fasisme terhadap bahasa. Dalam cuitannya di Facebook, Saut menulis; “Tugas sastrawan terutama penyair adalah menjaga dan menghidupkan bahasa. Oleh kernanya mari kita lawan facisme bahasa yang dilakukan kaum polisi bahasa macam Badan Bahasa itu dengan memakek semua kata dan frase yang menurut mereka salah tapi menurut kebiasaan dan frekuensi pemakainya adalah benar!”
Tampaknya, penyair Saut ingin mempertahankan kearbitreran bahasa dan eksistensi penutur supaya polisi bahasa seperti Badan Bahasa tidak semena-mena dan terlalu memiliki kuasa untuk memutuskan kebakuan dan ketakbakuan bahasa. Hal demikian juga sepertinya merupakan kritik terhadap institusi tersebut untuk lebih melibatkan sastrawan atau penyair sebagai rujukan ahli dan penasihat tertinggi bahasa.
Sebab, hanya sastrawanlah yang bergelut langsung dengan proses kekaryaan daripada akademisi yang hanya mendedah karya seperti laboran di laboratorium yang mencincang-cincang bunga untuk mengetahui hal yang terkandung, tanpa akademisi tahu terhadap kualitas karya dan bagaimana proses susah payah karya itu diciptakan. Dengan demikian, sastrawanlah yang paling dekat secara zahir maupun batin dengan bahasa itu sendiri.
Beberapa bagian atau keseluruhan dari pikiran dangkal di atas mungkin keliru, semoga ada yang membenarkan.
Penulis : Haikal Faqih
Penyunting : Alfiyatun Hasanah
Ilustrasi : Akhlada Nadzif N
seonggok homo unius libri