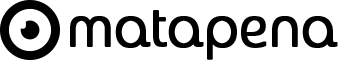Curhat yang Realis

Sebagai manusia yang sering merasa bingung dengan pertanyaan kepada diri sendiri, hal-hal kecil sekalipun akan selalu bergemuruh di otak. Tiba-tiba saja daftar pertanyaan itu tersimpan dengan rapih. Saya memeramnya di otak sampai hati pula. Makanya saya juga menjadi terlalu bingung mengapa saya begitu marah. Saya benar-benar marah kali ini. Boleh jadi dikata marah akan keadaan yang saya hadapi. Hendaknya jangan kecewa jika tulisan ini hanya berisi curhat. Harap maklum, namanya juga curahan hati ya kan.
Ibarat seorang pelukis maka kali ini saya ingin menyajikan lukisan yang cukup realis yang bebas. Artinya bebas untuk ditafsirkan. Menurutku, semester tiga bukanlah sesuatu yang mudah. Benar. Kita tidaklah hanya membaca abu-abu. Tapi juga nampak nampang campuran warna abstrak yang sukar ditelisik warna aslinya.
Literasi keduniaan dan hubungan sosial tidak lagi menjadi pelajaran anak SMA yang bisa dihadapi dengan duduk manis. Ah, itulah yang saya tahu. Banyak sekali ibaratnya, bukan? Karena pada dasarnya saya tidak tahu untuk memulai tulisan ini dari mana. Atau… Saya bisa memulainya dari uraian di bawah ini. Semoga bisa saya uraikan.
Hegemoni Itu Halus Bentuknya, Mungkin.
Memilih naskah untuk sebuah pementasan monolog bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi saya yang tidak pernah pentas secara sungguhan. Atau bukan hanya saya, mungkin sebagian besar orang di satu angkatan program studi saya. Bagi saya pribadi yang selama dua semester diajarkan untuk membikin banyak artikel dan terus-menerus melakukan kajian. Barang tentu bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu yang lama. Misalnya berguling-guling tidak jelas di kamar kos. Sambil menatap langit-langit atap. Hal itu dalam rangka memikirkan sebuah naskah yang cocok dengan diri.
Ketika saya berhasil mengantongi naskah yang terpilih, akhirnya saya mencoba mempraktikkan di depan dosen sebagai ajang latihan sebelum hari-h pementasan. Tiba-tiba penilaian awal yang saya dapatkan sangatlah jauh dari apa yang dibayangkan. Iya, hanya ucapan tak berdasar yang rasa-rasanya kurang akademis. Mengapa demikian? Menurut saya hal itu kurang menggambarkan bagaimana sebuah penilaian harus dilantangkan. Sebagai dosen dan akademisi tentunya, saya berharap bahwa komentar yang dapat saya dengar akan dinukil dari sebuah teori yang membahas tentang kesesuaian karakter. Namun, senyatanya tidak. Sejujurnya yang saya dapat adalah hegemoni body shamming yang terselubung adanya. Benar-benar halus untuk dapat dirasakan. Saya menyadarinya ketika pernyataan dilontarkan sambil mencoba memberi pembandingan dengan salah satu teman yang kebetulan membawakan naskah sama.
Lebih lanjut, saya sadar bahwa monolog adalah pembangunan karakter secara individu. Dan saya sama sekali tidak mendengar pembangunan karakter secara teoritis bahkan untuk tokoh yang akan saya pentaskan. Sebelum saya mementaskan naskah yang saya pilih, tentunya telah saya telusuri sebelumnya. Bagaimana karakter yang akan saya bangun melalui artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Tidak satupun saya membaca bahwa karakter yang akan saya perankan dapat dilihat dari fisiknya. Saya hanya menemui artikel yang berisi analisis kepribadian tokoh ataupun konflik-konfliknya. Itulah yang saya temui. Bukan penggambaran tokoh secara fisik misal hidung pesek, tubuh agak berisi, dan tidak tinggi. Saya tegaskan, ini khusus untuk naskah yang saya perankan.
Saya percaya penggambaran yang demikian ini, mungkin saja jika dapat kita temukan pada karya sastra lainnya sejenis novel ataupun cerpen. Bukan naskah monolog. Dalam naskah monolog lainnya mungkin ada, tapi tidak pada naskah yang saya pentaskan. Bahkan saya tidak menemuinya dalam kramagung naskah yang hendak saya pentaskan. Baiklah, lantas saya tidak berhenti di situ saja. Saya berusaha mencari sesuatu pembenaran akan ujaran yang dilantangkan terkait penilaian fisik karakter kepada saya. Mungkin saja ketidaktahuan juga sedang membersamai saya.
Keesokan harinya sebuah teori pada suatu artikel ilmiah kemudian dapat saya temukan. Artikel ilmiah tersebut mengutip sebuah teori yang dikemukakan oleh penulis naskah drama berkebangsaan Amerika. Namanya Lajos Egri. Katanya, manusia terdiri dari tiga dimensi yang membentuk dirinya, yaitu fisiologi, sosiologi dan psikologi. Dan inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan karakter tokoh dalam sebuah karya sastra.
Kemudian yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini, haruskah membandingkan dengan teman yang lainnya jika dengan teori di atas dapat memberi pemahaman kepada anak didiknya. Saya dapat memaklumi jika ujaran tersebut didasarkan kepada teori ini bukan malah membandingkan dengan mahasiswa lain yang kemudian malah merujuk kepada body shamming. Sejujurnya, hal itu justru dapat menimbulkan salah paham. Jika didasarkan pada teori maka saya akan percaya bahwa hal tersebut dijelaskan secara teoritis bukan hanya sekadar penilaian pribadi. Saya memiliki pembelaan yang demikian karena pada dasarnya, seperti yang saya katakan sebelum paragraf ini bahwa analisis tokoh yang saya perankan kebanyakan hanya dari segi psikologis dan sosilogis. Mungkin jika dosen tersebut dapat menjabarkan teori di atas, maka teori yang telah menggenangi otak saya sebelumnya akan gugur.
Saya pikir untuk dosen yang mengajar pada tataran sebuah universitas, saya akan banyak mendengarkan berbagai teori yang dapat dinukilkan kepada kami. Ini juga mungkin bisa menjadi acuan ketika kami yang berada di universitas bukan hanya sekadar praktik namun melakukan kajian-kajian.
Memikirkan Sesuatu yang Proporsional dan Sesuai
Nah, begini, mengingat praktik juga. Ada hal yang cukup mengganjal rupanya masuk ke dalam daftar pertanyaan saya. Mata kuliah yang saya tempuh ini mempunyai alokasi sks sebanyak 2 sks. Lantas bagaimana keterkaitannya dengan praktik? Menurut saya seukuran 2 sks yang ditempuh oleh mahasiswa kiranya tidak cocok dilakukan praktik sebesar parade monolog ini. Pementasan dengan disiarkan secara langsung di youtube. Lain halnya teman-teman yang berada di prodi dengan rumpun saintek. Mereka punya alokasi sebanyak 4 sks berikut dengan praktikumnya. Dan kami sendiri hanya memiliki separuh dari sejumlah sks itu. Rasanya seperti ngos-ngosan Dengan sistem yang demikian. Tidak masalah kiranya jika dipentaskan atau dipraktikkan di depan kelas, bukan dengan mementaskan secara besar-besaran di depan khalayak. Sehingga membuat kami begitu lelah mempersiapkannya. Apalagi kami tidak hanya menempuh satu mata kuliah ini saja.
Proyeksi yang Matang adalah Acuan
Hal lain yang masuk pada daftar pertanyaan saya adalah bahwa suatu hari saya mendengar perkuliahan tatap muka melalui zoom akan diadakan beberapa kali dalam rangka menyimak teman-teman kelompok lain. Mereka akan mempresentasikan sebuah materi yang dibagikan sejak pertemuan kedua mata kuliah. Bagi saya harusnya sejak awal pembagian kelompok harus disesuaikan dengan jumlah pertemuan tatap muka yang dilaksanakan. Sederhananya begini, mata kuliah ini diampu oleh setidaknya 3 orang dosen. Jumlah kelas yang ada adalah sebanyak 2 kelas untuk satu angkatan. Sementara itu, dalam satu semester ada sebanyak 16 pertemuan. Jika dibagi tiga maka setiap dosen punya kesempatan 5 kali pertemuan. Kemudian saya lihat lagi berapakah jumlah kelompok yang dibagikan. Maka tertera di sebuah file terdapat 6 kelompok pada setiap kelas. Jika disesuaikan dengan jumlah pertemuan dan setiap kelompok presentator sejumlah satu dalam sekali pertemuan maka terhitung lebih banyak jumlah kelompok yang akan presentasi. Bahkan saat diadakan zoom di luar jam mata kuliah, kelompok yang presentasi lebih dari 2 kelompok.
Ekspektasi “Berkuliah”
Beberapa hari lalu saya sempat berbincang ria dengan Sahabat Rizal dan sahabat lainnya melalui platform virtual. Kurang lebih dapat saya tangkap bahwa perbincangan tersebut membuat saya sadar, salah kiranya menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap bangku kuliah. Bahwa semisal akan ada banyak orang-orang pintar yang saling menimpali ilmu pengetahuan serta saling belajar. Saya juga sempat berpikir akan ada diskusi-diskusi maha dahsyat yang hadir di tengah-tegah akademisi kampus. Dan akan selalu ada teori-teori berdasar yang akan dibantah dengan teori lainnya sampai yang menimpalinya merasa kewalahan.
Ya. Lamunan saya berubah. Itu hanyalah ekspektasi sebelum saya benar-benar hidup di bangku perkuliahan.
Jadi, untuk menutup curahan hati dengan berkedok tulisan ini, pikiran saya yang bergemuruh ternyata juga berakhir pada sebuah kesimpulan. Meskipun banyak hal lain yang sebenarnya masih ingin saya jabarkan. Sebelum menulis tulisan ini, berhari-hari saya pusing dibuatnya. Mengingat banyak hal yang bergulat dalam diri. Mengingat falsafah “Adab terhadap guru”. Lalu mengingat lagi tentang fakta yang saya temukan tentang guru. Sejujurnya, saya sesekali mengingat tentang bagaimana kita harus ta’dzim kepada guru. Tiga tahun lamanya saya hidup di lingkungan sekolah yang menerapkan kultur pesantren. Saya masih mendapati bahwa haruslah menghormati guru bagaimanapun bentuk guru itu. Namun, bagi saya tidak lagi demikian. Meskipun sama-sama majlis ilmu antara pendidikan saya saat ini dan sebelumnya. Mungkin saja guru tidak lagi seperti yang saya temukan ketika dahulu. Jauh dari itu semua. Mungkin saya harus menulis ini sebagai sebuah penghormatan terhadap guru. Dan inilah yang namanya serba-serbi sifat manusia.
Salam hangat.
Penulis: Fatmawati
Editor: Haikal
Ini manusia yang hanya bahagia dengan berpikir sebanyak-banyaknya.