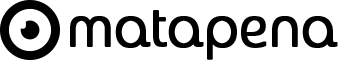Di Sebuah Kafe Paulo Freire Mengevaluasi

Education is freedom
Paulo Freire
Suatu pekan petang hari, seorang kating dari sebuah organisasi eksternal kampus menginisiasi para adiknya—atau kadernya—untuk pergi ngopi lepas isya. Bilangnya, “Mari ngopi, biar kita bisa saling dekatkan emosional dan berdiskusi banyak hal, utamanya buat maba yang mau melaksanakan ospek. Mumpung saya senggang dan gabut.”
Empat belas orang setuju. Beberapa belum beribadah isya saat berangkat ke kafe kecil di dalam gang, tidak ada kesan luks, yang ada malah kesan intelektualitas di sana. Di dinding, lukisan Chairil menyesap rokok bersanding dengan Einstein yang bengong. Beberapa quote sok bijak juga terpapang. Mereka memilih satu kafe seperti kafe-kafe lain yang menjamur di sekitar kampus yang sok-sokan menampilkan gambar dan siluet para intelektual yang klise: Chairil, Einstein, Soekarno, Gus Dur, Karl Marx, dan mungkin Rendra. Sebab, kalau siluet Hegel, Heidegger, Popper, Habermas, Levy-Strauss, hingga Lacan, para pengunjungnya mungkin tidak akan mengenalnya dan merasa tidak pintar, oleh karena itu tidak akan percaya diri saat mengopi dan memilin tembakau di sana.
Dalam perkumpulan tersebut, hanya dua orang yang memesan kopi hitam, selebihnya es coklat, stmj, susu, matcha, red velvet, dsb. Basa-basi basi dimulai dari pertanyaan kating tersebut kepada kader perempuannya, “gimana kuliahnya, lancar, nggak?”
Pertanyaan itu dijawab dengan ungkapan syukur tanpa perincian. Namun, segera disambar oleh teman berbadan cungkring dan bermuka tirus di sebelahnya. Sejawat berambut keriting itu berujar, “kuliah saja lancar, nalarmu mulai lancar nggak?” Kader perempuan itu merasa te-risak, mengancam akan menghilangkannya seperti yang terjadi kepada Widji Thukul—yang dinilainya berperawakan mirip.
Seperempat jam mereka ngobrol ngalor-ngidul membicarakan apapun yang terlintas di otak, berdiskusi, sesekali kating tersebut memberi nasihat-nasihat tentang kehidupan kampus. Ia menjelma sebagai orang bijak dengan sepak terjangnya yang segudang. Sampai ia memberi kesimpulan yang agaknya mengganjal untuk diterima akal seorang yang bermuka tirus berambut keriting. “Sering-seringlah ngopi, dik, supaya lebih pintar karena di situ kita bisa berdiskusi.”
Kating sampai pada kesimpulan tersebut karena sedari tadi melontarkan pendapat sering kali diawali dengan kalimat, “kata temenku pas ngopi kemaren, kata seniorku, bener apa yang temenku bilang …”
“Tapi jangan lupa, mas, sebelum ngopi, kita harus betah baca buku dulu, supaya ngopi kita berkualitas. Ngopi adalah satu kegiatan tukar-tambah pengetahuan, bukan cuma tambah & isi otak. Bukankah diskusi yang baik itu yang banyak diisi dengan dialektika, bukan berhamburan nasihat-nasihat? Lalu kenapa kafe harus banget diasosiasikan dengan pemikir? Mas saja tadi ngajak ngopi karena gabut, bukan?”
Angin semilir datang, tapi kating tersebut gerah. Ia memenuhi paru-parunya dengan asap tembakau sebelum mengangkat cangkir kopi, meminumnya. Ia hanya mengangguk, mukanya kecut. Terlepas dari itu, lima orang lainnya sedang keseruan bermain kartu, sisanya sibuk mengundang temannya ke dalam satu ruang pertandingan gim.
Si rambut keriting melanjutkan, “toh, kita bisa melihatnya: para pengunjung cuma main kartu seperti itu, minuman tinggal setengah ganti main gim. Minum minuman habis dua cangkir, merokok sampai bibirnya hitam dan nafasnya bau tembakau nggak hilang-hilang, begadang. Cuma begitu, kan? Mungkin lebih tepatnya, mereka mengunjungi kafe hanya untuk melegitimasi dirinya supaya kelihatan pinter, pemikir? Padahal yang pinter cuma temennya.”
“Jangan dengarkan dia, mas. Dia memang tidak punya attitude kalo ngomong,” sela kader perempuan sebelumnya, seorang dengan hidung dasun tunggal dan kedua pipi montok yang baru lulus dari kelas Studi Gender 2 sks.
Si kriting tertawa tak simetris, ia menjawab ketidaksukaan temannya dengan gaya bicaranya itu, “bentangkanlah pikiranmu seluas-luasnya. Karena orang berpikiran sempit sering kali melabeli orang lain enggak-enggak cuma karena perasaannya yang terganggu. Jangan hanya karena pikiran sempitmu tentang attitude, seolah-olah banyak orang yang nggak punya attitude. Jangan hanya karena pikiran sempitmu tentang gender & feminisme, sedikit-sedikit kamu cap laki-laki di sekitarmu dengan patriarkis. Menghakimi orang lain secara sepihak dengan menyebutnya patriarkis, bukankah juga tindakan patriarkis?” si kriting tak lupa juga menggiring arah bicaranya ke tema itu, sebab ia dari kemarin sudah jengah dikatain “patriarkis banget” hanya karena temannya itu tak mampu membalas argumen saat ia uji. Najis banget dikatain patriarkis sama orang yang baru belajar gender & feminisme kemarin sore, benaknya.
“Capai banget memang kalau berurusan sama Widji Thukul itu, mas.” Keberpalingan matanya seolah menyimpan dendam kesumat baru. Mukanya yang elok mulai guram.
Kali kesekian si kating meminum kopinya, hatinya berasa selesa. Sepertinya baru lahir sosok yang akan melanjutkan teriaknya pada demo-demo selanjutnya, dengan vokal lebih jernih.
“Hey, Bung, cuma main gim terus, nih, belajarnya kapan?” si kating pindah ke seorang yang Cuma suntuk bermain gim. Pemuda itu menoleh sebentar.
“Besok, mas, jam lima subuh. Jadwal kuliahku diutak-atik dosen.”
“Kenapa bisa?”
“Kenapa bisa? Pertanyaan bagus, mas. Feodalisme. Ya, itu jawabannya.”
“Aku nggak akan menyetujui pendapatmu selama kamu belum menerangkannya.”
“Begini, perasaan menjadi tuan membuat pendidik sering kali memonopoli ilmu pengetahuan yang menjadi sumber kehidupan mahasiswa. Mahasiswa harus mengabdi kepada mereka. Cara pandang seperti itu yang memunculkan sikap semena-mena. Kita sudah capai-capai KRS-an buat menyesuaikan waktu dengan kesibukan kita, malah kemudian tidak berguna. Mungkin benar Marxis bilang kalau feodalisme satu tingkat lebih maju dari sistem budak. Paulo Freire sudah bilang, kok, kalau pendidikan adalah kegiatan pembebasan, sebagai upaya memanusiakan manusia, karena pada dasarnya hak dasar manusia adalah kebebasan. Sedangkan kita harus menunggu waktu luang dosen buat ngadain kelas. Kelas tak lebih humanis daripada bermain gim.”
Asap kretek membubung, kating itu menyesapnya lagi. Matanya jatuh pada barisan lampu gantung kecil kafe paling ujung yang mati. Kalimat terakhir dari adik asuhnya tadi tampak mengganggunya.
“Mas, seminggu lagi saya osjur. Ngeri nggak, ya?” seorang mahasiswa baru bertanya tetiba. Pertanyaan yang merepresentasikan sikapnya yang lugu dan penurut. Perspektif dari mahasiswa penghuni ormek ingin ia dengarkan.
“Mesti marah-marah. Entah kapan mau diubah. Orang-orang psikologi bilang kalau kemarahan itu melepaskan energi yang negatif. Pendidikan tidak mungkin berhasil dicekoki dengan perantara daya amarah. Sebenarnya, mental itu apa sih? Terlalu subtil buat dibayangkan, sampai untuk membentuk mental kuat ia harus diasah dengan marah-marah. Seorang anak yang dididik orang tuanya dari kecil dengan marah-marah biasanya jadi pemurung, pendiam, tidak percaya diri, dsb., bukan mental kuat, yang ada mentalnya jadi sakit. Mereka tak kenal Paulo Freire.” Itu Widji Thukul yang menyuarakan pendapatnya.
Ia masih belum selesai, “Kalau toh cara pendidikan seperti itu dianggap perlu, penyelenggara bertanggungjawab untuk menyiapkan kurikulum, memilah mana yang akan diberikan kepada mahasiswa baru dan mengurangi bahasa kasar. Dalam upaya memberikan impresi dan pengajaran disiplin dan tegas, sepertinya sudah nggak relevan lagi dengan menyiapkan waktu khusus untuk diisi dengan kegiatan bentak-bentak dan marah-marah. Toh, dengan cara seperti itu mereka juga nggak memikirkan visi penanaman kedisiplinan kepada anggotanya, itu cuma buat gagah-gagahan dan mencitrakan diri sebagai senior yang berpengalaman menangani maba, kecuali kalau sebelum menjalankan pendidikan bentak-bentak semacam itu, mereka sudah mengantongi presentase keoptimalan dari cara didikan itu.
Memang benar setiap organisasi punya cara tersendiri untuk mendidik calon anggotanya. Tapi jangan lupa, kenapa banyak mahasiswa sekarang yang nggak minat masuk organisasi, karena cara didik dan kaderisasinya sudah usang dan kolot, tidak kompatibel dengan zaman. Karenanya, bila organisasi tidak adaptif dan segera menyesuaikan diri dengan zaman ia akan ditinggal. Apa mereka yang di dalam organisasi sudah mempelajari metode dan teori memberikan pelajaran, atau sebenarnya mereka malas belajar sehingga cara yang dipakai itu-itu aja dan tak lekas ada perubahan? Kritik dan otokritiknya kurang-lebih semacam itu.”
“Benar, kata orang bijak, sering kali kebenaran ditolak atau tidak diterima sebagaimana mestinya hanya sebab penyampaian yang salah, bukan karena kebenaran itu sendiri,” ujar yang oleh kating dipanggil “bung” itu. Widji Thukul merespons kembali:
“Common sense, apalagi di Indonesia, tampaknya memang membatalkan penalaran orang-orang untuk menggunakan akal sehatnya. Sering kali, common sense pada akhirnya dianggap sebagai bagian dari suatu ajaran atau nilai-nilai luhur yang harus dijalankan. Penerimaan ini adalah dengan apa adanya, bukan dengan selektif dan kritis.”
“Contoh lain, mengapa mereka tidak suka kepada kita secara turun-temurun? Apakah kita punya salah, ya? Bukannya orang kita dulu yang menghidupkan kembali saat organisasi mereka mati suri. Mereka mewariskan prejudice, prasangka buruk, tanpa dasar dan alasan yang mumpuni. Hanya karena kita sering mengkritisi kebijakan yang tidak adil, pelabelan tidak mengenakkan tak jemu disemai kepada mahasiswa baru yang lugu: apatis lah, arogan lah, dll.”
“Nggak apa-apa, pijakan kita kan setia pada proses, teguh terhadap prinsip.”
“Sudahlah, begini, dik. Osjur itu menyenangkan, tidak sesulit dan semenyeramkan yang kamu pikirkan. Nanti juga bakal tak bantu mempermudah prosesnya. Mereka semua adalah pelajar yang pintar dan kita harus tetap mengedepankan akal sehat. Saling benci & curiga itu tidak baik,” kating memberi nasihat bijak, maba itu mengangguk perlahan, lalu tertahan.
“Kebencian, curiga, monopoli, manipulasi, kuasa, serius … Dewasa adalah saat kita sangat susah untuk meminta maaf atau menerimanya. Makanya perdamaian di tangan orang dewasa tidak pernah terjadi. Orang-orang dewasa memang amat ganjil sekali,” seorang pendiam dari ujung menyambung, ia baru saja menamatkan Le Petit Prince.
“Ternyata kamu menyimaknya, ya. Penutup yang bagus untuk acara ngopi malam ini.” Si kating mengacungkan jempol tangan kirinya.
penulis: Haikal
ilustrasi: @suser_digitalart
seonggok homo unius libri