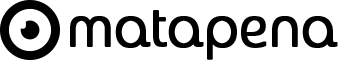Harusnya Aku tidak Memungut Kembang Kemboja itu
Sebuah cerpen karya Haikal F.

Sial. Kenapa harus sejengkel ini melihat sepasang nyamuk yang kawin sambil terbang berputar-putar di atas ubun-ubunku, hampir sejengkel ibu memasukkan benang ke lubang jarum saat menambal ujung kasur yang diam-diam dierat tikus, sebab aku dengan mata muda hanya mengulum senyum, tak ikut membantu.
Barangkali karena suatu itu, sejak sebulan terakhir ini kepalaku terus menggumuli suasana ketika aku memungut setangkai bunga kemboja yang jatuh di halaman. Sore basah tergelar kala itu, angin barat semilir, sejuk. Semua orang bahagia tentu saja, hanya dadaku yang menyisakan seruak getir sambil menghidu wangi bunga itu. Tekakku jadi terasa pahit.
Tatapanku sayu, dadaku dipenuhi pertanyaan peruntungan yang naif, inikah mungkin tempatku berteduh dari memulung sisa-sisa keriangan orang-orang? Bolehkah aku rengkuh untuk mengakhiri sebuah dahaga jiwa yang tampak abadi ini? Tentang harapan yang menunggu mati lepai, bolehlah kiranya aku siram dengan air mata kasih sayangnya yang seolah tersimpan baik di balik kedua pipinya yang padat.
Namun, buru-buru semesta memberi salam dan menjawab semuanya melalui isyarat angin yang berembus dari area sawah yang lapang. Menggerakkan pepadi, rerumput sepanjang pematang, pelepah nyiur, pohon jambu yang bengkok ke arah sawah, belukar di sisi jalan, rumput peking di halaman rumah, pohon kemboja kecil …
Semua bergeming.
Di kamar berbatas papan ini, sambil tiduran aku sering memikirkan betapa rasa dilema sering sekali datang saat aku mau memulai sesuatu. Aku selalu berbicara soal kepantasan. Kalau kurasa tak pantas aku tak akan bersemangat, dan aku memang tak pernah bersemangat sejauh ini.
Ketika suatu kali aku memohon untuk membeli buku RPAL di bazar buku sekolah, aku ingat ibu yang memakai daster kuning di depan tudung nasi bilang bernada dongkol, “kamu tidak perlu buku tambahan buat pandai menggarap sawah. Baca saja berulang-ulang buku yang ibu guru berikan. Kamu tak pernah bisa mau mengerti orang tuamu ini!”
“…kamu tidak perlu buku tambahan buat pandai menggarap sawah. Baca saja berulang-ulang buku yang ibu guru berikan…”
Lalu aku yang mulai suka pelajaran IPA waktu itu kembali ke kamar ini, memandang kosong ke tabel perkalian satu sampai lima yang ibu tulis dan tempel di dinding supaya tidak usah beli poster perkalian 1 sampai 10. Lalu aku berbaring seperti saat ini, mengiangi perkataan ibu seperti ketika aku selesai menangis. Apa artinya perkataannya? Yang pasti dari perkataan ibu itu, kalau aku selalu gagal memahami ibu yang masih tidak punya uang untuk mewujudkan mauku. Aku sedih. Pelan-pelan aku membenamkan keinginanku itu ke bawah bantal bersama yang lain, dan pergi tidur.
Di kelas esok harinya, aku meminta ibu guru menukar kelompokku yang kesemuanya pintar dan mempunyai buku RPAL.
***
Selesai makan sore itu, saat aku sudah duduk di kelas tujuh SMP, ibu mulai menyuruhku untuk ikut bekerja bersama bapak ke sawah orang-orang yang sedang panen padinya. Kebanyakan padi orang-orang memang sudah menguning runduk, sedang sawah sempit bapak sudah dipanen sebulan lalu dan kini belum dibajak lagi. Aku manut. Ikut menemani bapak memanen padi milik orang-orang, dari satu sawah ke sawah lain, berteduh di bawah caping camping, mengarit batang padi segenggam demi segenggam, merontokkan gabah dengan gebotan padi, memisahkan gabah dari kotoran dan daun padi, tak jarang hingga hari sudah gelap aku masih berjibaku dengan gabah, sering gatal-gatal karena miang meski berpakaian tertutup. Beberapa hari kemudian aku akan diupah, lumayan untuk aku tabung buat bayar keuangan di sekolah pada tahun berikutnya.
Tapi baru aku sadari kemudian, ibu seakan benar-benar tidak ingin aku menghabiskan waktu di sekolah, ia hanya ingin aku pintar mencari duit sejak dini. Aku menyadari itu setelah aku selesai melihat catatan merah di rapor sekolah. Aku tidak naik kelas. Di atas kasur ini aku yang menangis tanpa suara tetiba ingat satu hal, kenapa ibu dan bapak tidak memarahiku atas ini seperti masa-masa baru menginjak bangku sekolah dasar, saat aku nyaris tak naik kelas seperti tahun-tahun berikutnya. Kenapa keduanya tak memasang air muka kekesalan, penyesalan, kenapa justru hanya dielus-elus kepalaku supaya tidak payah menangis, supaya tidak cengeng sudah besar, supaya tak mempermasalahkan hal tidak terlalu penting ini. Keduanya bahkan tidak mau tahu betapa aku amat malu kepada teman-temanku yang lain. Pertanyaan yang tercekat karena tangis sedu sesenggukanku adalah, kenapa ibu menyuruhku untuk bekerja penuh seminggu sebelum ujian bahkan hingga ujian sekolah berakhir. Sungguh suatu itu aku tidak punya waktu barang semenit untuk membuka catatanku yang sering diprotes guru itu.
Beranjak ke kelas delapan, ibu dan bapak agaknya sudah acuh tak acuh melihatku tetap berseragam, tapi aku bertekad untuk menyelesaikan tingkat ini walau dengan malu dan segala keterbatasan. Bila ibu memberi uang jajan saat aku pergi ke sekolah selalu aku sisihkan untuk kubeli buku agar tangan tak lagi pegal menghabiskan banyak setip buat menghapus ulang buku-buku untuk bisa dipergunakan kembali.
Aku juga masih ingat tahun itu adalah saat bapak memiliki ide untuk membudidayakan itik alabio karena di rumah sepupunya ada sebidang tanah yang cukup untuk dibuat kandang. Akhirnya memang seminggu kemudian bayi-bayi itik sudah datang. Kudengar-dengar uang untuk membayar bibit-bibit itik dan membangun kandang diperoleh bapak dari meminjam ke pak Parman, bapaknya Anis. Anis menceritakannya dengan nyaring sambil mencibir aku di kelas saat UTS sampai aku urung meminta cairan koreksinya dan menjauh.
Tahun pertama banyak itik-itik bapak yang mati, kena berbagai penyakit, salah penanganan, salah asuhan, karena kami memang masih belum memiliki pengalaman memadai dalam mengurus itik. Usaha bapak bisa dibilang gagal, aku yang juga ikut mengurusi itu juga sedih, tanganku yang kuning habis memarut kunyit untuk campuran obat itik-itik yang sakit jadi lebih sering kutatap dalam mangu. Di rumah, ibu menyuruhku untuk tidak masuk sekolah sementara waktu supaya ikut membantu orang-orang yang panen bisa memperoleh hasil lebih banyak, agar bisa buat menutupi utang bapak kepada Pak Parman. Awalnya aku menolak, kemudian bimbang, gamang, lalu pasrah karena aku mulai sadar juga menanggung beban kehidupan ini.
“Hanya sekolah yang memberitahumu bahwa dibutuhkan banyak uang agar bisa mengklaim mimpi. Dengan kata lain, yang tidak punya uang tak punya mimpi. Apa kamu tidak pernah mencontoh Bagus yang banting-tulang membantu menggarap sawah bapaknya dan nyaris selalu sukses panennya. Mimpi itu juga bisa kamu temukan di sawah, tak melulu di sekolah, manja!” tukas Ibu ketika aku mengelap mulutku sehabis makan dengan kain serbet bekas daster miliknya. Bagus memang putus sekolah sejak ibunya pergi kawin lagi.
“…Hanya sekolah yang memberitahumu bahwa dibutuhkan banyak uang agar bisa mengklaim mimpi…”
Aku berhenti berdebat, aku mencoba lebih lunak dari ibu, ia memang keras kepala terhadap apa yang diyakininya benar.
Pada akhirnya aku putus sekolah sebelum sempat kuselesaikan jenjangku itu. Sudah terlalu banyak alpa yang kukoleksi dan akibatnya aku tidak berhak mengikuti ujian akhir. Mulai saat itu, aku merasa tak akan pernah pantas dan trauma dengan harapan, toh orang tuaku sudah menyediakan. Aku sedih, tapi itu omong kosong. Aku terus bekerja sekuat tenaga bersama bapak. Untuk panen padi kali itu untungnya tak terlalu terasa karena dipakai untuk menutupi utang pupuk dan pestisida yang mahal, dedak dan obat itik, serta menyicil tanggungan biaya ternak itik kepada Pak Parman.
Saat malam, aku kembali menatap langit-langit yang ini-ini saja; bekas baliho pendaftaran siswa suatu yayasan. Sering aku bayangkan berulang-ulang sesanti pak ustaz, bahkan sampai saat ini pun. “Sebelum bisa kenal Tuhan, terlebih dulu kamu harus kenal dirimu sendiri,” tutur beliau di surau dahulu sebelum aku berhenti pergi ke sana lagi. Aku terdiam. Meski tak sering salat, Tuhan adalah satu-satunya nama yang menyejukkan saat ibu dan bapak menyebut-nyebut kelebihan Bagus sesudah senarai kekuranganku mereka maki-maki. Tuhan sering menggantung di langit-langit kamar yang sunyi, sesanti pak ustaz akrab memenuhi kebisuanku.
“…Tuhan sering menggantung di langit-langit kamar yang sunyi…”
***
Rombongan pikap akhirnya tiba paling akhir. Aku langsung juga berebut melompat dari bak pikap karena gerimis turun makin tak ritmis, lalu berteduh di selasar rumah yang sudah dijejali ibu-ibu menenteng tenong dan bapak-bapak yang menyingsing sarung.
Beruntung gerimis tak berlangsung lama.
Sore berangsur mengambil alih. Dari arah barat lembayung sinar mentari jatuh tenang, hangat. Aroma petrikor menyeruak bersama beberapa ingatan. Beberapa menit setelahnya, penjamuan para tamu mengubah suasana menjadi lebih akrab. Berbincang, tertawa, diselingi mengisap rokok, menuang teh dan kopi ke lepek, sesekali bapak-bapak menyinggung cerita tentang kehidupan yang keras.
Dari arah timur, tiga bocah berbaju SD dan pramuka yang basah lewat sambil menyeret besi berani bekas salon rusak. Ditentengnya bersama segepok paku-paku karat dan besi bekas yang berhasil dikumpulkan dan masih bernilai jual. Di tangan bocah paling kecil kulat-kulat digenggam agar tidak jatuh. Rambut mereka selesai kuyup habis hujan-hujanan. Bocah seumuran mereka selayaknya sedang duduk manis di dekat jendela menikmati halaman rumahnya yang perlahan kuyup dan bias sinar matahari akan menyapu hangat tangannya, seperti yang dahulu sering kubayangkan. Aku harusnya bersyukur, batinku, rupanya tidak hanya aku yang mengalami hal macam mereka.
Kemudian seorang perempuan hampir seumuranku keluar lagi untuk menghaturkan sejumlah kue kepada tamu di pojok yang belum memperoleh bagiannya. Beberapa tamu memuji wajahnya yang ayu dan perangainya yang lembut, segelintir tamu lain yang sudah tak asing dengannya mengenalkannya ke kerabat lain. Tanganku memperbaiki kopyah. Kudengar, perempuan itu adalah adik dari mempelai lelaki yang akan menikah dengan anak dari sepupu bapak dalam waktu dekat.
Kali ini aku sempat melihat wajahnya, tapi ia melihat ke arah lain, ke sebuah kemboja kecil yang tumbuh di halaman rumahnya yang cukup megah. Angin barat menyapu wajah, telingaku semakin peka dari suara detak jantung yang tak keruan.
“Nak, apa bapakmu sudah memberi tahu kalau besok pagi kamu bantu-bantu aku tanam padi di sawah?” Pak Saiful yang menyela itu.
“Iya, Pak. Sudah diberi tahu tadi subuh,” kujawab.
“Besok aku tunggu di rumah.”
Aku mengangguk, perempuan di sana sudah tidak kelihatan lagi. Yang hadir malah ilusi pak ustaz di surau saat sedang menyampaikan sesantinya itu.
Kembang kemboja yang kupungut tadi memang terlalu harum dan terlalu halus. Tidak pas terlihat berada di telapak tanganku. Pola semestaku membawaku kembali kepada titik terapuh hidup ini.
*Dinda-Din, tinggal di desa Pasarejo.
Kuliah di salah satu Universitas di Jember.
seonggok homo unius libri