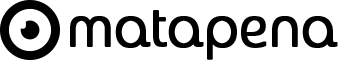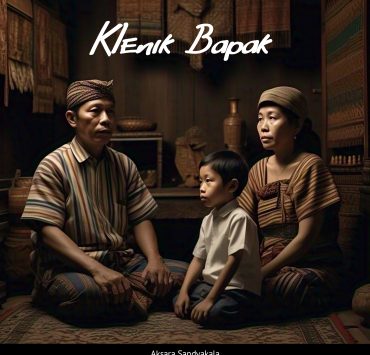Hujan yang Tak Pernah Reda

“Aku rindu.”
“Tenang saja, nanti dia pasti kemari.”
Perlu diketahui sebelumnya, bentuk rindu yang terbendung bukanlah atas kekaguman fisik yang dimiliki. Bukan pula manis ucapan yang membuai janji-janji. Toh, kita ini berbeda. Kami hanya sebagai pajangan untuk memperindah lahan yang mereka sebut taman. Kami yang selalu membendung rindu dan cinta hanya sebagai tumbuh-tumbuhan yang bersemayam, lalu ruang kami menaruh cinta adalah raga di setiap dini hari dengan bermacam-macam kumpulan kertas yang dibawanya setiap hari. Tidak selalu berbeda tiap hari, kadang ia membawanya dua atau tiga hari berturut-turut lembar yang sama. Kadang pula ia membawa lembaran yang usai dibacanya setahun lalu. Tapi bukan di sana letak cinta dan rindu kami. Saat ia mulai melihat-lihat secara bururutan kertas-kertas yang dibawanya, saat itulah kami mulai berpetualang ke dunia luar, mengikuti tema kertas yang dibawanya. Mengarungi banyak spesies asing, berkelana dalam pertunjukkan atom dan partikel lain, berjelajah hingga ribuan masehi di masa lampau untuk menyaksikan cerita orang-orang terhebat di dunia, dan yang paling menyenangkan adalah saat ia membuka buku yang tak pernah luput dibawanya, saat itulah kami bisa ikut bertemu Tuhan. Di sepanjang dini hari itulah cinta kami terletak. Pada cerita dan gigil perjalanan bersama raga yang selalu rela membuka mata untuk menjadi portal petualangan kami.
“Dini semakin gigil, sebentar lagi dia pasti datang!”
Benar saja! Raga itu sedang menuju tempat biasa ia membuka portal. Di tengah gigilnya angin dini hari, ia berselimut kain penutup dari kepala menjulai hingga lutut, kain dan bentuk pakaian yang biasa dipakai banyak raga ketika menghadap Tuhan demi menuntaskan kewajiban ataupun sekedar ingin cerita atau pula bermanja kepada sang Pencipta. Raga itu duduk, di bawah rindangan teman kami yang sudah mulai dipenuhi kembang merah jambu di setiap dahannya. Ia membuka dan mulai meneliti lembar demi lembar. Dan saat itulah, petualangan kami kembali dimulai.
Raga berpenutup kain yang menjulai hingga lutut itu bukanlah satu-satunya raga yang berpetualang bersama kami. Ketika mendekati panggilan subuh, ada beberapa raga yang berpetualang bersamaan, kebanyakan dari mereka untuk bertemu Tuhan. Meskipun bukan satu-satunya, tapi raga dini hari itu tetap terasa paling spesial, paling awal, terasa paling anggun, paling manja, dan paling banyak membuka bermacam-macam portal.
Petualangan kami sudah dimulai, tapi ada yang berbeda. Aura, suasana, perasaan, getaran, bahkan pompa jantung raga itu juga berbeda. Kulihat raga itu hanya sedang membaca selembar kertas sedikit banyak bekas tekuk. Semilir angin membasuh lekuk wajah itu, lalu terlihat jelas ia tersenyum lebar, amat lebar seperti mendapat kebanggaan luar biasa. Perasaan ini tak biasa. Gelayut jantungnya juga tak seperti biasa. Petualangan ini adalah pertama kalinya. Aku tahu, raga yang selalu datang dengan gigil dini hari itu sedang mengalami gejala cinta, sebuah perasaan manusia yang rentang sekali membuka pintu kemaksiatan. Tapi itu bukan masalah besar. Raga dini hari adalah salah satu manusia yang sangat gemar membaca kitab-kitab maaupun pelajaran formal, ia pasti akan kembali dengan beberapa buku penelitian lagi seperti waktu-waktu kemarin. Ia jugalah manusia biasa yang sudah sewajarnya merasa gelagat cinta.
***
Gerimis masih gemar turun, terkadang barayun-ayun pada angin untuk kemudian membasuh, terlempar, membasahi salah satu tempat mungkin di tanah, mungkin di lantai-lantai depan kamar-kamar, mungkin di dahan-dahan, mungkin juga merembes pada salah satu wajah dari raga-raga di langit sini. Kami makin subur. Rumput-rumput makin rajin meninggi. Beberapa dari kami sudah penuh rimbunan bunga hingga jika dilihat keseluruhan akan seperti kompetisi dengan kategori perlombaan tercantik dan terwangi. Semua terlihat indah, damai, bahagia, sebab wajah-wajah itu sering kali bersorak hore ketika pengumuman kelas kitab diliburkan akibat hujan yang terus menerus, masih tidak ada redanya. Tapi begitu dengan hujan yang gemar membuat basah bumi, rindu kami juga gemar membuat resah, seperti terus mencabik hingga tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain mengharapkan raga dini hari itu kembali. Ya, sudah sekitar dua bulan ini ia tidak berpetualang. Sesekali ia datang, duduk, membaca selembar kertas yang sedikit banyak ditekuk, lalu hanya senyum dengan gelayut cintanya yang menjadi portal kami satu-satunya.
“Aku rindu.”
“Entahlah, kapan ia kemari.”
Lalu malam semakin kelam. Gerimis masih rajin berjatuhan, seperti meringis atau mungkin tertawa, mengejek kami yang terlanjur sering menangis sebab kesekian kalinya dicambuk rindu.
***
“Kapan ia datang?”
“Untuk bermesra dengan cinta? Bahkan kita sudah lagi tak bertemu Tuhan”
“Itulah hati manusia. Cinta jugalah sebuah pemberian dari Tuhan yang maha cinta”
“Tak usah lagilah diharapkan. Ia tidak lagi membawa portal petualangan”
“Lalu, biarkan rindu terus mencabik kita?”
Taman semakin rindang. Malam belum begitu kelam, sepeti hujan yang tak begitu keras, mengasilkan gerimis yang rapih jika dilihat dari cahaya lampu-lampu jalan.
Rindu semakin menikam-nikam.
Kelas kitab libur lagi. Hampir seluruh raga bersorak, lalu masuk ke dalam kamar masing-masing. Mungkin bercengkrama dengan raga-raga lainnya, mungkin menarik selimut untuk kemudian membangun mimpi-mimpi, mungkin juga membuka buku untuk membaca kertas-kertas materi atau menorehkan tulisan-tulisan sastra, curhatan, juga mungkin gambar sederhana yang sedang mewakilkan suasana hati.
“Biasanya ia mampir. Sekedar membaca materi, ataupun merampungkan tulisannya”
“Lalu pada dini hari ia akan datang lagi”
“Rindu akan selalu keras”
“Sampai kapan kita harus menahannya? Sebelum kita mati dicabik rindu”
“Sebelum kita mati layu”
“Manusia sering lalai, mudah terjerumus”
“Lalu bagaimana?”
“Biarkan saja, nanti Tuhan yang akan memanggilnya, entah dengan perasaan rindu atau dengan sakit yang mereka hanya bisa mengadu pada Nya”
Gelap semakin kelam dan dingin semakin gigil. Gerimis semakin gemar, lalu menjadi hujan. Hujan menjadi deras, sangat deras, sederas rindu yang menikam taman, juga sederas tangis raga-raga yang gagal mengartikan bahasa rindu dari Tuhan mereka.
Penulis: Wilda Indana Lazulfa