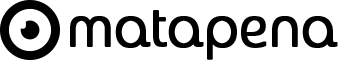KELUGUAN

(Sebuah esai terhadap cerpen Pelajaran Mengarang karya SGA)
Seno Gumira Adjidarma berhasil menangkap satu realitas yang tak begitu sentral namun cukup sekali untuk menerangkan kompleksitas peristiwa di belakangnya. Seno, seorang pengarang yang menggaungkan mekanisme pemanfaatan medium cerpen atau karya sastra secara umum sebagai alternatif untuk mengkritik kekuasaan saat pers dibungkam, pada praktiknya kali ini ia mulai dengan melancarkan kritik sosial yang barang tentu pangkalnya terdapat pada gerak-gerik penguasa yang gagal melahirkan kesejahteraan rakyat.
Seno mengungkapkan secara garis besar bagaimana proses kreatifnya dalam mengarang cerpen “Pelajaran Mengarang”-nya itu. Dalam bukunya berjudul “Trilogi Insiden” Seno menjelaskan ketika suatu hari ia membaca majalah “Hai” edisi 5 November 1991 dan menemukan cerpen terjemahan berjudul Nona Fich karya Alfed Hitchcock yang membuatnya begitu terkesan, lebih-lebih kepada bagaimana teknik yang dipakai Hitchcock itu. Cerpen itu berkisah tentang seorang anak kecil yang menemukan mayat seorang perempuan dan menceritakannya di muka kelas dalam sesi pembelajaran “bercerita tentang pengalaman hari ini”, tapi tidak ada yang memercayainya, termasuk ayahnya yang dilaporkan. Pada akhirnya, si anak kecil menyeret untuk menyembunyikan mayat perempuan yang ditemuinya di gorong-gorong karena tidak ada satu pun orang yang memercayai apa yang ia lihat.
Selepas membaca cerpen itu, Seno mulai berpikir dan berimajinasi untuk mempraktikkan teknik dari cerpen yang mengilhaminya menulis “Pelajaran Mengarang” itu. Namun, terlihat begitu kontras antara kasus yang Seno angkat, yaitu tentang masalah kemiskinan kultural akibat dari kebijakan buruk yang berlarut-larut, dari pada hanya masalah keluguan seorang anak kecil hasil dari Hitchcock.
Seperti galib, dalam cerpen, seorang pengarang hanya bisa memotret satu peristiwa saja, akan tetapi, dalam satu peristiwa tersebut tetap bisa mewakili peristiwa lain yang kompleks. Mengawali ini, Seno seolah mengingatkan pembaca, bahwa acap kali ada efek domino yang timbul dari segala peristiwa, apalagi dari kebijakan pejabat Negara.
Terlepas dari hal itu, biarlah menjadi renungan para pejabat menggunakan hati paling bersih mereka. Tugas saya di sini tak lebih hanya untuk menambah upaya persuasif yang sudah digaungkan oleh Seno empat belas tahun lalu dengan menghadirkan suatu “cemooh” cerita yang terkesan mengolok-olok ketidakbecusan penguasa.
Apa yang Seno hadirkan dalam cerpen “Pelajaran Mengarang” ini tak lain bermuasal dari kepekaannya—untuk tidak menyebut kejenuhannya—dalam melihat realitas di sekitarnya dan dibarengi dengan caranya memanfaatkan momentum yang pas ketika menemukan idenya.
Cerpen ini berkisah tentang seorang anak SD di dalam kelas saat sedang pelajaran mengarang berlangsung. Ibu gurunya memberi tiga opsi judul yang bisa dipilih oleh murid-muridnya, yaitu “Keluarga Kami yang Bahagia”, “Liburan ke Rumah Nenek,” dan “Ibu” dengan batas waktu mengarang yang sudah ditentukan. Namun ketimbang teman-temannya yang lain, Sandra, tokoh utama dalam cerita ini kebingungan memilih salah satu dari ketiga opsi judul yang pas dengan apa yang ia rasakan dalam hidupnya selama ini.
Saat ia membayangkan keluarga yang bahagia, di kepalanya hanya terbayang rumahnya yang sangat kotor dan jorok yang sering disambangi oleh pria-pria yang ingin menikmati jasa ibunya. Ketika ia membayangkan liburan ke rumah nenek, ia hanya teringat seorang perempuan yang berdandan menor ketika ibunya menitipkan pada perempuan itu mana kala ibunya pergi ke luar kota berhari-hari. Apalagi untuk menuliskan seorang ibu dengan pria-pria yang senantiasa datang-pergi ke rumahnya untuk menikmati jasa ibunya. Pikiran semacam itu seharusnya masih tidak boleh berada dalam otak seorang bocah sekolah dasar. Saat semua temannya sedang asyik dengan karangannya masing-masing, Sandra masih sibuk menaruh rasa jengkel kepada ibu gurunya. Ia tampak kesulitan bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Trauma diam-diam sedang berkelindan di sekitar kepalanya.
Digambarkan betapa miris, seorang anak sekolah dasar yang masih lugu begitu turut memikul aib sosial ibunya sehingga kegiatan masa kecilnya yang seharusnya senantiasa bahagia, ceria, dan penuh gairah direnggut begitu saja oleh kontaminasi persoalan hidup seorang dewasa. Jadi ketika seorang Sandra diceritakan memandang gurunya dengan rasa jengkel tentunya tidak boleh disebut sebagai tindakan nakal. Sebab, hal itu adalah cara dia sebagai anak kecil yang lugu mengekspresikan tanggung jawab pikiran di luar kemampuan pikirannya. Tidak bisa memungkiri luka dan keberguncangan psikisnya sedini usia itu yang ia dapat saat di rumah.
Praksis kita mengetahui di sini, betapa persoalan kemiskinan kultural pun bisa menjadi pengganggu terhadap keluguan seorang anak kecil. Faisal Oddang menceritakan bagaimana anak-anak di Rumania dihancurkan keluguannya. Profesor Dorel Zaica melakukan riset kepada anak-anak yang lahir sebelum kepemerintahan otoriter Nicolae Ceausescu. Usia anak-anak sekitar sembilan tahun disodori pertanyaan, apakah air mata itu? Apakah senyuman itu? Apa prangko itu? Semua dijawab dengan bahasa paling sederhana berdasar apa yang indera mereka tangkap mengenai ketiga hal di atas. Memasuki masa pasca revolusi Rumania itu anak-anak yang tumbuh diberi pertanyaan serupa, tetapi jawabannya berbeda; logis dan rasional, tidak sekadar apa yang indera mereka tangkap belaka. Artinya, mereka telah mengganti keluguan dengan rasionalitas yang diperoleh dari informasi yang meruah dari media-media.
Kenapa keluguan bisa penting? Mengutip bagian akhir dari tulisan Faisal Oddang berjudul “Belajar dari Keluguan”, cerpenis itu mengatakan, “… bahwa hidup yang rumit sering kali lebih mudah dihadapi dengan cara berpikir sebaliknya. Dengan lugu, dengan kembali dan meminjam cara pikir kanak-kanak.”
Seno memulai elaborasinya dari sana, dari keluguan seorang anak yang terjebak dalam ambivalen. Dari gejala keluguan itu, Seno mengajak pembaca bisa mendeteksi permasalahan yang lebih besar dan kompleks. Mulai dari cara seorang ibu menghidupi anaknya dengan melacur. Diceritakan juga bahwasanya sering ketika akhir pekan, ibu Sandra akan mengajaknya pergi ke mall dan membelikannya apa yang ia mau, duduk dan melihatnya sendu layaknya pandangan seorang kepada anak yang penuh kasih sayang, sama sekali berbeda dengan sikap ibunya ketika ia menanyakan siapa bapaknya, atau ketika ia masuk lewat pintu depan sedang ibunya sedang bersama seorang pria.
Naluri keibuan, sisi lembut dan kasih sayang rupanya masih dimiliki oleh ibu Sandra sebagai ejewantah dari etika kepedulian seorang feminin. Bisa kita sinyalir bahwasanya latar belakang ibu Sandra melacur adalah faktor keterimpitan ekonomi.
Pelacuran menjadi masalah sosial di Indonesia sebab, banyak perempuan yang jantung penghasilannya untuk menghidupi hari-harinya bergantung pada pekerjaan ini. Tentu apabila pendidikan warga negara baik, maka dengan sendirinya akan memunculkan lapangan pekerjaan baru karena orang yang memiliki pendidikan cenderung memiliki pekerjaan yang mumpuni alih-alih melacur. Banyak perempuan melacur berkedok terimpit kehidupan dan pekerjaan itu adalah satu hal paling efektif bagi orang pemalas dan tidak memiki kompetensi kerja mumpuni. Dan negara bertanggung jawab dalam hal pendidikan yang buruk dan susahnya mencari lapangan pekerjaan. Di sini kita bisa melihat betapa Sandra, bocah kelas 5 SD turut memikul beban negara di pundaknya.
Pada akhirnya, dengan segenap sisa keluguan dan ketakberdayaan, ia mengatakan dalam secarik kalimat bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Sebuah cerita ironi di antara tumpukan cerita-cerita bahagia teman-temannya yang lain. Barangkali yang dikatakan Pangeran Cilik karya Antoine de Saint-Exupéry benar adanya; “orang-orang dewasa memang amat ganjil.”
Oleh: Haikal Faqih (Mahasiswa Sastra Indonesia & anggota Rayon PMII FIB 2021)
seonggok homo unius libri