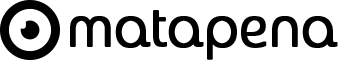Klenik Bapak

Jawa, tanah yang terhampar seperti kain tenun yang indah, beriring benang aura mistik yang tak pernah terputus mewarnainya. Di sini, logika mistika masih berkuasa, seperti seekor burung yang terbang membawa pesan yang tersembunyi di balik awan yang gelap.
Bapakku, seorang pria yang telah menempuh setengah abad perjalanan hidup, telah mengumpulkan pengalaman mistik yang bejibun. Beliau, tak terlepas dari hal-hal mistik, yang telah melekat menjadi bagian dari darah dan dagingnya. Serupa pohon beringin yang tumbuh di tepi sungai, akar-akarnya telah merambah jauh ke dalam tanah, seperti itulah gambaran ilmu magis bapak, mencari sumber kemistisan hidup yang tak pernah kering.
Bapak terlahir dari keluarga yang sangat kental dengan budaya mistiknya. Mengalir dari akar yang terjalin erat dengan tanah Jawa purba, itulah bapak, di mana kabut mistik adalah bahasa ibu, sedang pusaka leluhur adalah bisik dalam setiap denyut nadinya.
Kakek bilang, Bapak terlahir sungsang pada usia kandungan yang belum genap tujuh bulan, “bagai kuncup senja yang merekah sebelum waktunya, hadir di dunia saat rembulan belum genap menyinari tujuh purnama, sebuah keajaiban di antara keheningan dan doa.” Itulah kata indah yang terucap dari bibir kering kakek, bapaknya bapakku.
Menurut kepercayaan Jawa, orang yang terlahir sungsang seperti Bapakku, bakalan memiliki kehidupan yang seperti labirin, penuh dengan lika-liku dan kejutan yang tidak terduga. Mereka yang terlahir dengan cara seperti itu, dianggap memiliki hubungan yang erat dengan alam spiritual. Bapakku, memang persis sekali dengan penjelasan itu, memiliki kehidupan yang nyeleneh dan mistis.
***
Meski terlahir dari suluh yang membakar dupa dan merapal mantra, jiwaku tak terikat olehnya, aku hadir di dunia ketika mesin telah bernapas, toh aku juga terlahir normal tidak seperti kelahiran Bapak yang dipenuhi magis.
Tidak ada yang istimewa dari kelahiranku, kecuali bahwa aku terlahir dengan kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri.
Pernah pada suatu obrolan santai, Bapak menuturkan kisah tentang diriku yang berusia lima tahun, kala itu. Bapak bilang, aku kerap bermain dengan kembaranku. Lidahku kelu, dengan nada terkejut, “haa…kembaranku?” hingga astor di mulutku jatuh ke lantai bagai daun yang gugur. Lantas aku pun bertanya tentang saudara kembarku itu. Sontak bapak tersenyum tipis, “klenik,” kata yang keluar dari mulutnya.
Ternyata, eh ternyata kembaran yang beliau maksud adalah makhluk astral, “hmm… benar dugaanku, Bapak hanya membual.” Alisku bertaut, namun jemariku tetap setia pada toples astor yang aku pangku.
Bapakku mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik awang-awang, bahwa aku memiliki sedulur kakang dan adik yang tidak kasat mata. Aku, yang masih berada di dalam kegelapan ketidaktahuan, bertanya dengan nada yang cuek, “Emang iya?”.
Bapak lantas menjelaskan dengan santainya, seperti seorang guru yang mengajar murid, sambil menghisap seputung rokok kobot di mulutnya, yang mengeluarkan asap hingga membumbung tinggi ke langit. “Kakakmu dipanggil Kakang Kawah, sedang adikmu namanya Adi Ari-Ari”, katanya dengan nada yang tenang. Detik ini aku baru sadar bahwa yang dimaksud Bapak adalah konsep Sedulur Papat Limo Pancer, yang mengajarkan kita tentang keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan.
***
Pernah sekali dalam jengkel yang membuncah menyaksikan Bapak yang berbisik pada hening, terlontar dari bibirku kalimat lancang, “ngomong sama maruta, Pak?” Namun, bapak hanya tersenyum melihatku tanpa berucap sepatah kata pun.
Di balik skeptisisme ini, mengalir ajakan Bapak menelusuri akar Jawa. Beladiri, budaya, tradisi, bahkan ajian tak pernah kutolak. Bukan karena keyakinan, melainkan karena takut mendurhakainya, selagi tidak merugikan diri dan orang, toh pasti ku jalankan.
Malam itu, saat Bapak mewariskan ajian Pecah Gilang, sebuah mantra yang konon mampu meremukkan batu sebesar dan sekeras apapun. Beliau berujar, “Laku ini hanyalah lelucon sukma, Nak. Hanya kepiawaian untuk mengusir sepi.” Keraguan terpahat di wajahku, namun bibirku membungkam. Kemudian, di hadapanku, Bapak memperagakan sabdanya.
DUARRR!
Sebongkah Gilang, sebesar kendi, luluh lantah terkena tamparan telapak tangan Bapak, namun relung batinku berseru, “Sandiwara belaka”. Bagiku mungkin itu hanya trik yang dimainkan Bapak saja.
Di bawah ardawalika, Bapak membimbing aku dan paklikku, adiknya bapak yang juga gemar menyelami samudra mistik, untuk duduk bersila diatas pupus daun pisang yang ranum. Sambil komat-kamit, bapak menyuruh kami menirukannya melafal mantra, ajian klenik.
“Adung Aliata’, Ata’ Aliadung… Niyat ingsun… Matak aji…” Seolah kami sedang memanggil sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Demikianlah sabda itu mengalun, terlarang bagi telinga Awam, sebab, kata Bapak, dapat merenggut kewarasan.”
***
Senja usia tak menggerogoti kelincahan Bapak dalam mewariskan Pencak Macan Putih, beladiri pencak silat warisan leluhur kami.
Dalam gelapnya hutan malam, gerak bapak terlihat seluwes panthera, sorot matanya, setajam Candrakirana yang menyibak kelap malam.
Sejak saat itu, niskala terkuak; aku mulai percaya bahwa Bapak adalah orang yang mampu menjalin hubungan dengan astral, yang tidak bisa diraba namun dapat dirasa kehadirannya.
Di sela peluh dan lelah, kami merebah di sebuah gubuk renta yang bersemayam di antara gerumbul gadung dan pating. Sunyi kian merajam sukma, seiring malam menutup Candrakirana.
Tiba-tiba, Bapak berdesis, “Kau ragu, bukan? Saksikanlah…” Tanpa angin, tanpa hujan, 3 pohon pisang di samping gubuk roboh di hadapanku. “Dhuh, Bapak kula pasrah,” lemas aku dibuat kejadian itu.
***
Sejak malam itu, aku tidak lagi mau mengikuti Bapak ke hutan yang gelap dan ladang yang sunyi, bukan karena takut akan kegelapan atau kesunyian, tapi karena aku tidak ingin terjebak dalam labirin logika mistika yang semakin dalam dan semakin kompleks. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri dalam pusaran kepercayaan yang tidak terbukti.
Meski demikian, aku masih mengamalkan ajian dan mantra-mantra pengasihan yang menurutku masih memiliki nilai dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Aku menganggapnya sebagai doa yang dapat membantuku dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, aku dapat mempertahankan keseimbangan antara mistik dan rasionalitas.
— Sandi Bima Seta.
Ilustrasi: Aksara Sandyakala
Jember, 9 Februari 2025