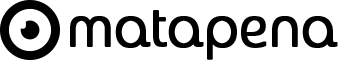“Mempertanyakan (Kembali) Stigma Buruk Terhadap Aktivis”

Bangun tidur tadi, saya agak kaget ketika mendapati kiriman link blog dari salah satu kawan saya. Melihat judulnya yang menarik, “Jangan Langsung Terpesona dengan Laki-laki Aktivis, Ketahui Juga Sisi Gelapnya.
Saya langsung mengunjungi blog tersebut dan membaca tulisan itu dengan khusyuk, sesakma dan dalam tempo sesantai-santainnya. Saya tidak tau ini tulisan jenis apa, dikatakan opini atau esai tapi nilai subjektivitasnya lumayan keterlaluan dan kelewat batas. Dikatakan artikel tapi ketika saya membaca tidak ada satupun sumber legal yang bisa ditekan validitas dan kredibilitasnya. Saya rasa, tulisan yang diniatkan penulisnya untuk mencerahkan dan mengkritisi fenomena malah keluarnya menjadi tulisan sampah yang keruh dan kaku. Katanya, Voxpop adalah akronim dari bahasa latin Vox Populi yang berarti ‘suara rakyat’. Tetapi, kenapa tulisan yang tidak memihak rakyat sama sekali itu justru lolos sidang redaksi? Sungguh ironis. Jujur, membaca tulisan itu saya malah bingung. Lebih bingung dari membaca bab 7 buku Madilog tentang ilmu bukti. Saya berfikir, mungkin saya saja yang terlalu dungu dan kurang menyerap intisari tulisan tersebut. Walaupun, memang tulisannya memang beneran ‘jelek’ sih. Tidak tidak, saya bercanda. Oke, baik kita akan mencoba mengkritisi dan mempertanyakan (kembali) tulisan tersebut.
Pertama-tama, saya mau sungkem dulu pada penulisnya. Mau tidak mau saya juga harus mengapresiasi, karena beliau sangat masif dan begitu kenceng menulis tentang perlawanan perempuan dan isu-isu seksis. Namanya Dea Safira, perempuan glossy yang mengaku sebagai feminis Jawa dan juga (kebetulan) adalah seorang dokter gigi. Sungguh perfeksionis sekali mbak Dea ini sampai-sampai berani melabeli ‘sisi gelap’ aktivis, secara sepihak. Dalam tulisan ini juga saya bermaksud meminta izin untuk berlaku skeptis pada berondongan tulisannya yang cenderung menyerang dan logosentris.
Saya cukup tertarik ketika membaca di paragraph kedua, menurutnya, tidak semua aktivis faham betul tentang pemahaman gender, ditambah statement “Belum tentu mereka yang terlihat garang di podium lapangan memahami relasi kuasa dengan pasangannya.” Betul, saya mengamini hal tersebut. Tidak semua aktivis faham tentang gender. Tetapi apa hubungannya mbak Dea? Itu adalah dua hal yang berbeda. Yang satu permasalahan relasi pengetahuan, yang satu urusan personal. Itu adalah dua komponen yang berbeda, tidak ada nilai kausalitasnya sama sekali. Aktivis yang bergerak langsung ke lapangan dan jalanan, bukan semata-mata ingin disebut sebagai lelaki tulen yang super-maskulin. Dia juga kadang remuk tak berkutik jika kekasihnya tiba-tiba cuek sebab ditinggal demo. Seaktivis apapun lelaki, dia juga pernah ambyar, mbak. Asal mbak tau, mereka ke jalan secara sadar dan tidak kosongan, mereka selalu dituntut untuk membawa cita-cita mulia serta nilai kemaslahatan yang harus terus disuarakan dan diperjuangkan.
Dan juga ingat mbak, aktivis tidak melulu laki-laki, banyak kok perempuan yang jadi aktivis. Mbak pernah lihat tragedi Kendeng dan Lekardowo? Bagaimana melihat sosok perempuan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan lingkungan? Dalam mata akademisi, fenomena ini dinamai Ekofeminisme, saya rasa mbak lebih faham. Satu lagi, aktivis itu prestise mbak, bukan jabatan. Tidak seperti PNS. Jadi, tuduhan mbak itu bisa merebak kemana-mana, dan siapa saja bisa kemungkinan merasa.
Mbak Dea juga berkata, “Pada kenyatannya, banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan ketika berpacaran dengan aktivis.” Mbak Dea yang tersayang, saya boleh minta data yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai masalah ini? Boleh kok kita adu data, kita sama-sama kaum (yang dikatakan) intelektual mbak. Jadi, saling judge seperti ini malah memalukan serta akan mengkebiri pemikiran diri sendiri. Apakah kekerasan selalu berangkat (dilakukan) pada diri seorang aktivis? Ini pertanyaan paling fundamental yang harus dijawab mbak Dea terlebih dahulu. Biar tidak terkesan hanya nyinyiran saja, juga agar tidak seperti gelembung kosong yang berjalan.
Mbak Dea saya rasa terlalu terburu-buru merampungkan tulisannya agar dibaca serta mendapat banyak aplaus juga rating teratas karena merasa telah menulis tema sensitif dengan gagap gempita, walaupun lemah. Di tulisan itu, Mbak juga bilang “Bahkan, ada laki-laki aktivis yang sudah faham feminisme tapi masih melanggengkan kekerasan.” Lagi-lagi, Mbak Dea terlalu sibuk mencari data-data buruk yang entah dari mana asalnya. Mungkin dengan cara searching google dan mengetik “sisi gelap aktivis” lalu ditulisnya tanpa melakukan observasi keterlibatan sama sekali. Saya yakin kok, mereka yang sudah faham betul mengenai konsep feminisme (Kartini menyebutnya sebagai emansipasi) akan berfikir dua kali bahkan tiga kali untuk melakukan kekerasan, lebih-lebih terhadap perempuan.
Walaupun ketika meminjam Nietzsche dalam konsep The Will to Power-nya, “Pengetahuan itu selalu terkait dengan kehendak berkuasa.” Memang tidak bisa dipungkiri, jiwa patriarki lelaki selalu melekat pada dirinya. Tetapi kita juga tidak bisa diam saja, kita bisa meredam hal itu dengan kajian-kajian kecil dan memberi pemahaman secara berkala mengenail keadilan dan kesamarataan. Bahkan ada statement yang sangat radikal dari ahli psikoanalisis terkemuka, yang ternyata adalah seorang dengan pemikiran patriarki banget, Sigmund Freud. Dia mengatakan “Perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna.” Ditambah muridnya, Erich Fromm dalam buku ‘Cinta, Seksualitas dan Matriarki’ “Tidak pernah ada emansipasi bagi perempuan, perempuan hanya mencoba merebut wilayah eksklusif laki-laki”. Ini selaras dengan pemikiran Marx bahwa “Kehendak untuk menyetarakan adalah kehendak untuk menguasai.” Silahkan mbak Dea tafsiri wacana-wacana global dari para pemikir itu. Ingat mbak, jangan hanya dilihat kulitnya saja, tapi lihat juga latar belakang mengapa konsep tersebut bisa meluncur ke permukaan. Saya yakin, Mbak dea adalah seorang perempuan yang seneng baca. Jadi, bolehlah sebelum menulis membaca terlebih dahulu. Tidak hanya buku, fenomena dan realita sosial juga bisa dibaca kok mbak. Eh, jadi ceramah.
Yang lebih lucu lagi dari tulisan ini, mbak Dea mengatakan “Ada salah satu aktivis yang rajin mengggelar diskusi mengenai keadilan gender, namun karena ia takut terhadap masa depannya jika memiliki anak, ia memaksa pasangannya untuk aborsi.” Lalu ada lagi, “Ada juga aktivis yang tak mau berusaha mencari nafkah untuk anak-anaknya, sehingga istrinya yang terpaksa harus banting tulang mengerjakan beban ganda menghidupi keluarga.” Mba Dea yang ‘pintar’, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada anda sebagai penulis perempuan, mbak Dea bukan hanya memukulrata, tetapi mbak Dea telah ‘mengkufuri’ fakta sejarah tentang bagaimana aktivis senantiasa menjadi mitra kritik dan pengawas berjalannya pemerintahan, dari zaman represivitas Soeharto hingga hari ini. Mereka akan menangis ketika membaca tulisan mbak Dea yang amat ngawur ini. Saya bukan bermaksud mengglorifikasi masa lalu, tetapi saya ingin mengajak sampeyan mengenang sejarah biar melek. Anda bukan hanya ‘jahannam’ dalam tulisan, tetapi juga dalam pemikiran. Contoh kasus anda hanya dilakukan orang-orang dari oknum tertentu, dan anda langsung menggeneralisasi begitu saja. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar aktivis yang idealis, aktivis yang mengetahui betul makna hidup dan berlaku baik? Atau hanya mantan aktivis abal-abal? Banyak kok sekarang aktivis yang memilih pragmatis jadi DPR padahal dulu begitu idealis dan mentereng-tereng berbicara di microphone aksi demonstrasi. Fahruddin Faiz dalam ‘Ngaji filsafat’nya menamai fenomena semacam ini sebagai ‘proses dialektis’.
Soe Hok Gie pernah berpesan “Yang paling aman, (jika mau mengikuti arus) bekerjalah di suatu perusahaan yang bisa memberikan sebuah rumah kecil, mobil, atau jaminan-jaminan lain dan belajarlah patuh pada atasan. Kemudian carilah istri yang manis. Kehidupan selesai.” Mungkin contoh ini yang dijadikan landasan berfikir seseorang yang dahulunya aktivis tetapi sekarang ikut membebek pemerintah tanpa perlawan ketika terjadi ketidakadilan. Kasus-kasus yang diatasnamakan Mbak Dea sebagai aktivis tersebut tak lebih dari sebuah upaya untuk memonopoli kenyataan dan kebenaran massa. Mbak Dea seolah-olah menulis ‘sisi gelap‘ aktivis hanya sebatas permasalahan selangkangan. Tidak mencoba untuk mengkonotasikannya kepada permasalahan yang lebih luas dan kompleks seperti dari sistem sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan masyarakat. Dan juga, anda hanya memaksakan studi kasus tersebut untuk membantu memperkuat pendapat anda yang lemah. Saya rasa, jika memang benar dia adalah (mantan) aktivis, dengan perlakuan keji semacam itu. Anda tidak sepatutnya menggasak hal satu, sama dengan yang lain. Malah terkesan memperlihatkan bahwa anda adalah penulis petasan sumbu pendek.
Mbak Dea juga memberi pesan yang cukup baik “Saran nih, jangan langsung terbuai dengan laki-laki aktivis maupun perempuan aktivis. Betul, persoalan kekerasan dan ketidakadilan tidak terikat jenis kelamin.” Sungguh saran yang tidak konkrit dan tidak beralasan. Mbak Dea, para aktivis tidak ingin lawan pasangannya terbuai kok. Aktivis punya jalan cerita cinta sendiri (uwu). Atau jangan-jangan saya curiga, mbak Dea menulis ini karena sebal dan pesimis sebab ingin pacaran dengan seorang aktivis namun tidak kesampaian? Atau mbak Dea patah hati karena dulu pernah punya mantan aktivis? Mungkin praduga saya salah, walaupun kemungkinan benar. Hehe. Maaf mbak, bukan bermaksud mengajak bernostalgia.
Mbak Dea juga berbicara mengenai kapitalisme sejati. Dia ngomong, “Bentuk kapitalisme paling kecil adalah mulai dari keluarga, yaitu eksploitasi perempuan atas dasar ‘kasih sayang’.” Menarik memang, tetapi apa hubungannya dengan sampeyan? Lucu saja, diksi ‘eksploitasi’ disejajarkan dengan diksi ‘kasih sayang’. Jauh, seperti Sabang dan Merauke. Dia juga memberi pesan di paragraph terakhirnya, “Tapi, kalau kamu ingin sekali bercita-cita bisa berpasangan secara setara dengan aktivis, pengusaha muda, pekerja. Pastikan kamu berjalan di sampingnya. Buka di belakang, terus memikul beban dan tanggung jawabnya.” Lagi-lagi, ini adalah doktrin tersirat. Mungkin akan timbul pertanyaan satir, “Apa mbak Dea ini pernah menikah dengan jenis 3 lelaki di atas. Sampai-sampai berani mendikte dan menggurui?”
mbak Dea seolah-olah hanya berusaha memprovokasi orang-orang dengan pengalaman ngelantur agar sesuai dengan apa yang distigmakannya. Sama sekali tidak bersifat empiris. Mau menikah dengan siapa saja kan hak personal mbak. Kenapa anda mau masuk dalam circle personal seseorang? Siapa tau, ada pasangan yang justru lebih suka membantu kekasihnya memikul beban dan tanggung jawab bersama agar menciptakan keluarga yang gotong royong dan samawa (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kan, lagi-lagi mbak Dea bersikap seperti buzzer. Sebelum saya izin meninggalkan tulisan ini, denger-denger mbak Dea lagi menghilangkan diri (deactivate) dari salah satu akun sosmed ya? Karena dimintai klarifikasi sebab memberitakan kabar fitnah (hoax)? Aduh mbak, sial banget ya. Kita harus hati-hati loh mbak di era sekarang. Kebenaran menjadi bias, dia bukan lagi kebenaran, tetapi kesalahan yang diulang-ulang. Dan di waktu yang sama, akhirnya muncullah klaim kebenaran. Saya juga mau nanya mbak Dea, apakah mbak Dea pernah dengerin lagunya The Panasdalam feat Jason Ranti yang berjudul “Gundah Gulana Pacar Aktivis”? Asyik tuh mbak lagunya.
Terakhir, saya membuka diri kepada siapa saja untuk mengkritik, tidak sepakat ataupun melawan pendapat saya (yang bukan saya, karena sudah dicemari oleh saya yang lain) dari tulisan ini. Terutama seluruh tim redaksi voxpop.id, saya tidak bermaksud aneh-aneh, hanya mencoba untuk meluruskan tulisan mbak Dea yang awur-awuran dan mosak-masik bangunan narasinya. Terimakasih, salam sayang!