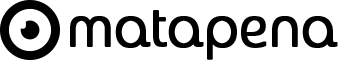Sahur Pakai Apa Malam Ini?

Suka dan memang sering kesepian
Huruf pertama tulisan ini saya ketik tepat pukul 18.30, saat saya sedang memikirkan, akan masak apakah saya nanti buat makan sahur? Menentukan menu akan masak apa sahur nanti sebenarnya hampir sama dengan menentukan akan makan sahur dengan menu apa nanti. Bedanya, selain menentukan menu, kamu juga harus bisa membagi anggaran yang sudah dipatok agar bisa cukup—tentu menyesuaikan dengan kemampuan masakmu.
Tapi bukan cerita itu yang ingin saya tuliskan di sini. Akhir-akhir ini saya agak merasa, maaf, risih dengan orang-orang yang menyisakan seperempat, separuh, bahkan tidak jadi makan dengan alasan “tidak nafsu” atau ”tidak enak”.
Makan, sebuah “ritual” untuk menyambung hidup. Kegiatan yang seharusnya menjadi hal yang paling diprioritaskan juga seringkali malah dianggap sepele. Kesakralannya lenyap oleh rutinitas dan esensinya sirna tergerus distraksi. Kapan terakhir kali kamu murni makan, tanpa kamu sambi dengan scrolling beranda media sosial atau menonton sesuatu?
Setidaknya dua hal itu yang perlu kita renungi bersama. Pertama, soal bagaimana kita menghargai makanan. Kedua, soal bagaimana kita menikmati makanan.
Pertama, soal menghargai makanan. Saya paham bahwa kamu merasa berhak untuk tidak menghabiskan atau tidak jadi makan makanan yang sudah tersaji di depanmu.
“Toh makanan ini aku beli memakai uangku sendiri. Uangku pun juga kudapat dari jerih payahku sendiri!” batinmu sambil mengernyitkan jidat.
Benarkah demikian?
Baiklah, anggap saja saat ini kamu sedang memegang sepiring nasi dengan siraman sayur asam dan lauk tongkol bumbu merah serta dua buah kerupuk—asem, sepertinya saya sudah menemukan menu apa yang akan saya masak nanti, haha!
Mari kita mulai dengan piring. Siapa yang membuat piring? Tentu kita tahu bahwa untuk membuat piring, buruh-buruh di pabrik bertarung dengan lelehan kaca panas untuk mencetak lalu mengepakinya. Setelahnya, distributor mengirimkan piring-piring hingga kemudian sampai di tanganmu.
Selanjutnya nasi hangat yang asapnya mengepul menghangatkan mukamu. Persoalan nasi bahkan jauh lebih kompleks. Para petani menjemur punggung di sawah untuk merawat biji-biji gabah sampai melahirkan biji-biji gabah yang baru. Setelahnya, pabrik penggilingan menjemur biji-biji tersebut untuk kemudian digiling; biji-biji gabah kini sudah menjadi biji-biji beras. Bebijian beras kemudain dipak dan didstribusikan. Tapi tidak semudah itu, sebelum sampai pada tahap ini, bebijian ini pasti sudah menyaksikan dan mengalami banyak hal: mulai masalah pupuk sampai kebijakan harga.
Selanjutnya sayur asem segar yang menyiraminya. Untuk dapat menyajikannya, setidaknya dibutuhkan sayuran, asam, lengkuas, daun salam, bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, gula, dan garam. Tak perlu ditulis, saya rasa kamu sudah dapat mengerti prosesnya.
Dari yang sudah tertulis di atas, setidaknya bisa kita ketahui siapa saja yang berperan untuk menyajikan nasi dan sayur asem yang terhidang di hadapanmu. Para petani, pabrik piring dan semua orang yang ada di dalamnya, pabrik pupuk dan semua orang yang ada di dalamnya, sampai pemerintah yang menentukan kebijakan hal-hal tersebut—dan jangan lupa yang masak!
Lalu terakhir ikan tongkol (semoga tidak terpeleset membacanya), bukankah nyawa para nelayan di laut bahkan yang menjadi taruhannya?
Artinya, jika kamu menyia-nyiakan makanan yang sudah tersaji di depanmu, sama saja kamu menyia-nyiakan usaha orang-orang yang sudah tersebut di atas.
Tapi mungkin kamu masih bisa bersikukuh bahwa itu tetap hakmu untuk tidak selera makan atau menyisakannya.
“Hei, aku membelinya loh, dengan uangku yang kudapat dari jerih payahku sendiri loh! Dan orang-orang yang kamu sebutkan di atas tadi sudah mendapat haknya dengan uang yang mereka dapatkan!” kali ini kamu tidak hanya mengernyitkan jidat, tapi agaknya ponselmu sudah ingin kautaruh karena jengkel, “ndak masyok!” tambahmu.
Uang, benda yang kata Yuval Noah Harari adalah imajinasi kolektif paling sukses manusia.
“Tidak bisa kita makan dan minum, tapi kita berhasil membayangkannya menjadi sesuatu yang bernilai,” tuturnya dalam wawancara lima bulan lalu dengan Gita Wirjawan.
Memiliki uang seringkali membuat manusia merasa menjadi makhluk paling hebat. Kertas-kertas, logam-logam, dan angka-angka inilah penyebabnya. Bukan, sih, maksud saya cara manusia menganggap dan mempergunakannya yang perlu dikoreksi. Uang, entitas intersubjektif ini berhasil membuat individu merasa hanya dirinyalah yang subjek, sementara individu lain hanya objek.
Tetapi daripada ndakik-ndakik membahas itu, sepertinya saya ingin bertanya saja kepadamu. Apa yang mau kamu beli jika para petani enggan menjual berasnya? Apa yang mau kamu beli jika nelayan enggan menjual ikannya? Dan apa yang mau kamu beli jika orang-orang enggan menjual barang atau jasa hasil produksinya?
(Luqman: 18) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
Sudah, ya? kiranya itu sudah cukup menghapus noda pikiranmu soal “hak menyisakan makanan” dengan alasan tidak nafsu belaka.
Kedua, soal menikmati proses makan. Idealnya, saat makan kita mengambil sesuap hidangan yang tersaji, menyuapkannya ke mulut, mengunyahnya perlahan sambil menikmati enaknya nasi, gurihnya daging tongkol, dan segaranya sayur asem. Namun, kapan terakhir kali kamu “merasakan” hal tersebut? Saya yakin yang ada di pikiranmu dan yang kamu rasakan saat makan adalah sesuatu yang kamu tonton di gawaimu, bukan hal-hal tersebut.
Inilah yang disebut dengan “mindful eating”, atau mungkin lebih mudah kita sebut sebagai “kekhusyukan makan”. Menikmati proses makan tanpa gangguan apapun, hanya fokus makan. Ini perlu dilakukan untuk mengembalikan sakralitas proses makan. Lebih bagus jika ditambah dengan memikirkan hal-hal yang sudah dibahas di awal: peran dan upaya orang-orang yang menghasilkan alat dan bahan makanan kita. Percayalah, makanmu akan lebih nikmat dan berkualitas jika hal ini dilakukan, daripada disambi dengan melakukan hal-hal lain.
Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa khuyuk menikmati makanan akan lebih memaksimalkan penyerapan nutrisi, meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan stres, bahkan tidak akan terjebak dalam diet kronis. Tidak perlu dijelaskan di sini karena penjelasan lebih rinci akan muncul jika kamu mengetikkan “mindful eating” di Google.
Sebagai penutup, cocok kiranya jika kita mengenang-kenang ucapan ibu kita saat membujuk agar kita menghabiskan makan.
“Ma’eme kudu entek, lho. Lek gak entek ngko pitike mati!—makannya harus habis, lho. Kalau tidak habis, nanti ayamnya mati!” sambil menyuguhkan sesuap makanan di depan mulutmu lalu kamu mempercayainya dan lekas mau makan lagi.
Bukankah ibumu dulu juga pernah menasihatimu untuk menghabiskan makananmu tanpa sisa karena kalau masih tersisa walau sebutir, nasinya akan menangis?
“Lek gak resik ngko segone nangis, lho—kalau tidak bersih nanti nasinya menangis, lho!” dan kamu tidak pernah mendengar tangisan itu.
Terakhir, makan dan kekhusyukan menikmati prosesnya pada akhirnya akan menuntun juga pada bersyukur. Tak henti-hentinya saya mengingat-ingat sabda Nabi bahwa sebaik-baik doa adalah bersyukur.
أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ
Ketika sudah bersyukur, tinggal kita nanti janji Tuhan dalam firmannya di Surat Ibrahim ayat 7, “jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmatmu”.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ
Sekian. Saya sudah memutuskan akan memasak sayur asem dan tongkol bumbu merah. Jadi, saya mau belanja dulu dan lanjut memasak—dan kiranya tulisan ini sudah layak untuk menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan ke saya: “saya pingin nulis, tapi saya bingung mau nulis apa?” Lah, saya tadi gak kepingin nulis, kok. Saya bingung mau masak apa lalu menuliskannya, tetapi dengan menulis saya malah menghasilkan dua hal: renungan ini dan keputusan nanti mau masak apa.
penulis: Rizki Hasan
ilustrasi: Cindy Virda
Suka dan memang sering kesepian