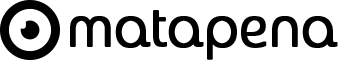Selamat Tahun Baru: Apa yang Selamat dan Apa yang Baru?

Tahan sebentar, mungkin agak terkesan sensitif ketika membaca judul tulisan ini. Saya hanya ingin mengajak bermain-main (logika) dan bercanda (dialektika), tapi tetap dengan (agak) serius. Jika alkisah pada suatu hari ada seorang penyair yang mati bunuh diri sebab sajak-sajaknya tak mampu mengubah realitas sekitar seperti apa yang diharapkannya, lalu yang menjadi pertanyaan paling awal sebelum saya lebih jauh masuk ke dalam, tulisan ini sebenarnya untuk apa dan siapa? Saya tidak akan bertele-tele dan berpanjang lebar menyoal permasalahan “Apakah boleh umat islam mengucapkan tahun baru?”, “Umat islam haram merayakan tahun baru”, atau yang lebih klise “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka termasuklah ia di dalamnya.” Jujur saja, saya agak risih mendengar demikian. JIka umat islam selalu memakai paradigma berfikir semacam itu, maka benarlah kata Sultan Ibrahim (pendiri partai Murba, Tan Malaka); mereka tidak akan pernah benar-benar berkembang dan progresif! Ketika bangsa barat sudah mulai berencana dan mendiskusikan kloning manusia dan migrasi antar planet, kita masih saja berkutat pada permasalahan syariat yang berumit-rumit. Umat Islam kudu visioner dan dinamis dahulu Soekarno pernah berdoa dalam salah satu suratnya, “Ya Allah, jadikan aku orang yang paling dinamis.” melihat arus pergerakan zaman, perdebatan kusir semacam itu seharusnya sudah tuntas dan selesai. Jika kita meminjam kredo Soekarno dalam Islam Sontoloyo-nya, kurang lebih begini “Apa yang bisa kita petik dari kitab suci? bukan apinya, bukan semangatnya. Namun debunya, fesesnya.” Nyatalah apa yang dikhawatirkan Soekarno, ketika kita melihat fenomena hari orang-orang lebih menuhankan kebenaran dan agamanya masing-masing daripada menuhankan Tuhannya. Saya tidak bermaksud liberal apalagi punya fikiran untuk bertindak sekuler, saya hanya mencoba untuk menjadi manusia beragama yang dinamis dan fleksibel seperti apa yang dicita-citakan Soekarno dan Tan malaka. Meski mereka acapkali berbeda pandangan, Soekarno yang penuh pertimbangan sementara Tan Malaka yang mudah resah. Mereka tetaplah pemikir berlian bangsa ini sekaligus founding fathers yang tetap mentereng-tereng. Baiklah, prolog yang membosankan. Kita masuk dalam pembahasan yang jauh tidak lebih penting.
Kalimat “Selamat Tahun Baru” dalam Analisis Semantik
Sebagai mahasiswa yang (kebetulan) masuk dalam jurusan ilmu bahasa, mau tidak mau saya harus menerapkan sedikit demi sedikit ilmu ke-bahasa-an saya untuk merespon realitas yang ada, agar tidak dianggap sebagai manusia yang sibuk dan terkungkung pada bahasa itu sendiri. Maka saya mencoba untuk mendedah sedikit demi sedikit mulai dari hal yang sederhana, ada satu konsensus ringan yang harus difahami, saya tidak mau membenar-benarkan ataupun menyalah-nyalahkan apa yang sudah ada. Walaupun secara teknis prosedural saya belum (cukup umur) menempuh ilmu semantik dalam kelas perkuliahan, di pesantren dulu saya sedikit banyak sudah mulai dikenalkan perihal seluk-beluk ilmu bahasa. ada yang namanya ilmu Nahwu, sintaksisnya Bahasa Arab. ilmu Shorof, morfologinya Bahasa Arab. Tajwid, Fonologinya Bahasa Arab. Dan untuk semantik, istilah Arabnya ialah ilmu balagah (ma’ani). Dulu saya belum menyadari hal itu, tetapi ketika saya masuk perkulihan, pada akhirnya saya agak mulai ngeh. Meskipun belum faham betul. Tetapi yang dapat saya simpulkan, pada dasarnya prinsip semua bahasa itu sama, dalam hal pengimplementasiannya saja yang agak berbeda, dan pasti itu tidak jauh.
Baik, kita preteli satu-satu. Jika kata ‘selamat’ diucapkan, makna yang hadir biasanya adalah tentang perayaan ataupun peringatan. Seperti dalam ungkapan ‘selamat’ ulang tahun, posisi subjek di sana adalah orang yang merayakan atas bertambahnya usia (berkurangya umur) dan pengharapan-pengharapan. Begitupun dengan ungkapan ‘selamat’ pada perayaan hari Raya, baik Nyepi, Natal ataupun Idul Fitri. Di sana ada proses perayaan atas kemenangan, dan juga refleksi dan muhasabah diri atas perayaan tersebut. Lalu ketika kita mengucapkan ‘selamat’ pada momentum pergantian tahun, apa yang sebetulnya kita rayakan, peringati dan kita menangkan? Pertanyaan sederhana yang belum sempat terfikirkan atau bahkan terjawab sampai nanti pergantian tahun selanjutnya. Saya jadi teringat humor cerdas Gus Mus “Kalau hari-harimu, hari inimu dan kemarin-kemarinmu sama. Untuk apa engkau memelihara calendar dan ikut memusingkan pergantian tahun?” satire yang menohok dan cukup menampar, setidaknya bagi saya sendiri. Pembacaan saya pada kalimat Gus Mus kurang lebih, ungkapan ‘selamat’ setiap pergantian tahun baru bisa dianggap layak dan mempunyai nilai hakiki yang lebih jika keluar dari mulut manusia-manusia yang berusaha beresolusi menjadi lebih baik, setidaknya baik untuk dirinya sendiri. Saya tidak bermaksud ceramah, saya hanya mencoba menyambungkan apa yang saya fikirkan dengan ungkapan Gus Mus tadi. Lagi pula, saya toh masih begini-begini saja. Belum ada hal bisa saya anggap sebagai suatu yang revolusioner dalam hidup saya. Jika dibandingkan dengan mereka yang lebih produktif dan berani hidup melebihi saya.
Sementara, frasa ‘tahun baru’ apabila kita mengkritisinya dalam point of view semantik historis, sebenarnya tidak pernah ada hal yang dapat dikatakan baru dan kreatif. Tahun hanya berlalu, berjalan dan berganti. Angka 2020 sebelumnya sudah pernah dipakai pada tahun 2000. Jadi konklusinya, tidak ada yang benar-benar baru di tahun ini jika dilihat dari sisi struktural. Remeh memang, tetapi bila difikir lebih dalam kita akan menemukan semacam proses ‘penyadaran‘ apabila mengaitkannya dengan kepribadian dan cara kembang berfikir seseorang. Jadi, siapa yang mengawali istilah ‘tahun baru’ di dunia yang amat fana ini?
Terakhir, saya berpesan: selamat mengawali tahun 2020 dengan bahagia, semangat dan penuh percaya diri. Mari bersama berdoa, semoga Tuhan menambahkan kita kepekaan, kebijaksanaan dan rasa empati. Dialah tempat tumbuhnya tiga hal itu, semoga ketiganya selalu menjadi landasan dan arah moral kita.
*Tulisan ini selesai dalam kurun waktu satu tahun.
1 Januari 2020.